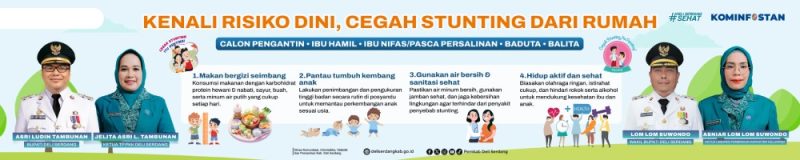Yandi Syaputra Hasibuan, S.S.
Manusia adalah makhluk yang menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal (homo ludens). Umumnya bahasa digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan.
Dalam beberapa tahapan, bahasa selalu mengalami transformasi dari zaman ke zaman. Banyak istilah-istilah yang digunakan manusia untuk menggambarkan atau mempersingkat pesan yang ingin disampaikan.
Sebagaimana disebutkan Yuval Noah Harari dalam “Sapiens”, penggunaan istilah merupakan suatu keahlian yang dianugerahkan kepada manusia dalam beradaptasi terhadap lingkungannya secara simultan.
Di antara sekian banyaknya istilah yang digunakan oleh manusia belakangan ini adalah “pembantu” dan “asisten.” Bila dilihat secara etimologi kata “asisten” sebenarnya kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yakni “assisten”.
Kalau ditelaah secara mendalam, penggunaan kata asisten hanyalah sebuah kosa kata untuk memperhalus bahasa. Sebab ada istilah yang lebih tua lagi, yakni “slave”, dapat diartikan sebagai budak.
Budak dalam Kamus Bahasa Indonesia Mutakhir artinya anak-anak; jongos; gajian; dan hamba. Jika dipahami secara general, berarti semua orang adalah budak, sepanjang ia masih disuruh oleh orang tertentu dengan imbalan tertentu pula.
Lantas, mengapa perubahan istilah ini bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya?
Sebelum beranjak ke arah sana, pada dasarnya manusia hanya mengganti kata “budak” menjadi “pembantu” atau “asisten”. Praktiknya sama saja, mereka tetap saja disuruh oleh tuannya untuk mengerjakan apa yang diperintah dengan imbalan uang.
Lebih mengerikan lagi, praktik tidak manusiawi ini pernah dialami seorang TKW di Arab Saudi, yang sempat menghebohkan publik. Menurut penuturan sang TKW, ia disiram dengan air panas, kulitnya disetrika, dan mendapat perlakuan tidak manusiawi.
Padahal bila kita membaca “Sirah Nabawiyah, karyanya Al-Mubarakfuri”, budaya Arab memang penuh perbudakan, tetapi budak ini dicintai diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.
Budak dalam budaya Arab dipekerjakan sebagaimana mestinya, seperti membersihkan rumah, menggembala kambing, dan ikut tuannya berjualan ke pasar.
Budak-budak ini tinggal di rumah tuannya. Kadangkala jika sesama jenis budak itu diangkat menjadi saudara, dan jika berbeda jenis (laki-laki dengan perempuan) mereka itu kemudian menikah.
Tentang budak ini, walaupun budak pernah mendapat siksaan, seperti Bilal bin Rabbah pernah mendapat siksaan dari kaum Quraisy, tetapi hal itu hanya untuk menguji Islam yang disebarkan Nabi Muhammad SAW. Apakah Islam akan membantu orang yang lemah atau tidak.
Selain itu, praktik perbudakan sebenarnya sudah lama terjadi. Bila kita membaca buku Herodotus (Histories), ia menjelaskan tentang perang antara Sparta (Yunani) dengan pasukan Xerxes (Persia). Perang ini juga dikenal dengan Parsi.
Bala tentara yang dibawa Xerxes untuk menggempur pasukan Sparta sebagian besarnya adalah budak. Karena pasukan Xerxes ini berperang bukan untuk kebebasan, tetapi lebih karena rasa takut pada sang raja, pada akhirnya pasukan Persia pun kalah. Apalagi sekak awal jiwa mereka memang sudah diperbudak.
Mengapa terjadi perbudakan? Praktik perbudakan terjadi karena ada perang (ekspansi) wilayah oleh seorang penguasa. Ketika wilayah itu ditaklukkan, maka orang yang masih hidup dan tertangkap dijadikan budak oleh yang menang perang.
Dalam perkembangannya, bila merujuk tulisan Anthony Reid (Asia Tenggara dalam Kurun Niaga), ia menguraikan faktor-faktor terjadinya perbudakan. Di antaranya karena keturunan budak, tidak sanggup membayar hutang, jual-beli budak, dan meminta perlindungan.
Demikian halnya bila kita membaca tulisan Edwin Loeb (Sumatera: Sejarah dan Perkembangannya), ia menambahkan satu faktor mengapa terjadi perbudakan, yaitu karena melarikan diri lalu kembali ditangkap.
Di Pulau Jawa belum diketahui pasti kapan muncul istilah perbudakan, mengingat budaya Jawa sangat patuh terhadap raja atau atasannya.
Menurut Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya berjudul “Jalan Raya Pos, Jalan Daendels” (2005), istilah budak bukanlah orang-orang yang tidak mendapatkan haknya untuk menjadi manusia merdeka, dengan alasan karena ada kuasa yang lebih tinggi daripada masyarakat umumnya sehingga mereka diperintah atau menjadi pesuruh. Misalnya kolonialisme yang dijalankan oleh Daendels membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan.
Di belahan dunia lain, seperti di Amerika Serikat, sejak abad ke-17 banyak orang diculik dari Benua Afrika dan dipaksa menjadi budak. Diperkirakan orang Afrika yang pertama dibawa berjumlah 19 orang dan mendarat di Virginia sekitar 1619.
Selama abad ke-18 diperkirakan terdapat 6 sampai 7 juta orang Afrika yang dijadikan budak di Amerika. Para budak tersebut umumnya dieksploitasi untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau maupun kapas (Kompas, 1 Juli 2021).
Senada dengan itu Pemerintah Kolonial Belanda turut melakukan hal yang sama pada orang-orang Afrika pada abad ke-19 dan 20. Hal ini dicatat oleh Ineke van Kessel dalam bukunya berjudul “Serdadu Afrika di Hindia Belanda 1831-1945″.
Pada dasarnya mereka akan dijadikan sebagai tentara KNIL. Namun di luar itu mereka juga dijadikan pekerja kasar seperti memperbaiki transportasi militer, jalan, dan membasmi kaum pemberontak yang secara militer hal ini bukanlah bagian kerja pokok KNIL.
Profesi budak sendiri beraneka ragam. Mereka yang bekerja di pelabuhan untuk mengangkut barang-barang dagangan dapat dikategorikan sebagi budak pada abad ke-15 hingga 17.
Selain itu, mereka yang bekerja di sektor pertambangan dapat juga dikategorikan sebagai budak. Mengapa demikian? Karena mereka tunduk dan patuh kepada penguasanya, mereka ini pun bekerja atau suruhan tuannya.
Dalam abad ke-20, praktik perbudakan mulai dihapuskan karena banyak kritik dari para kaum intelektual humanis. Dalil menghapus praktik perbudakan disebabkan karena manusia harus diperlakukan setara. Walaupun praktik perbudakan di dunia belum secara total habis, tetapi kritik kaum humanis menjadi cikal-bakal usainya konsep perbudakan.
Lantas, bagaimanakah kondisinya pada abad milenial seperti saat ini? Benarkah praktik perbudakan sudah dihapuskan, tanpa memperhalus bahasanya saja?
Menurut hemat penulis, pertanyaannya ini dapat terjawab jika sesama manusia menganggap masing-masing dirinya setara. Tidak ada pihak yang dominan maupun subordinat, dan kapan hal itu dapat terjadi? Hanya waktu yang bisa menjawab, tidak dapat kita tentukan itu kapan terealisasi.
Penulis adalah Mahasiswa S2 Program Studi Ilmu Sejarah, FIB USU