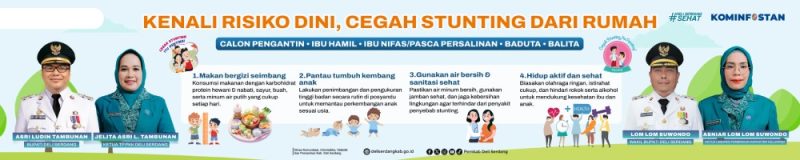Oleh: Nazira Aulia Az-Zahra
Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Sumaterapost.co | Lampung – Pemilu 2024 menandai titik balik dalam lanskap politik elektoral Indonesia. Hasilnya bukan hanya menunjukkan siapa yang menang atau kalah, tetapi menggambarkan perubahan arah ideologis dan preferensi politik publik yang semakin kompleks. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang telak dengan mengantongi 95.989.300 suara (58,6%) dan mendominasi 36 dari 38 provinsi. Kemenangan ini bukan semata-mata hasil personalisasi figur, tetapi juga manifestasi dari strategi politik nasionalisme baru yang merangkul keberagaman, populisme, serta modernisasi kampanye digital.
Sebaliknya, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mencoba mengusung gagasan perubahan, hanya menang di dua provinsi: Aceh dan Sumatera Barat, wilayah yang dikenal memiliki tradisi Islam politik kuat. Pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD yang mengandalkan PDIP dan citra nasionalis-modernis, bahkan tidak menang di satu provinsi pun, termasuk di Jawa Tengah yang selama ini disebut sebagai “kandang banteng”. Hal ini menjadi indikasi kejenuhan pemilih terhadap figur lama dan narasi klasik nasionalisme yang dianggap tidak cukup menyentuh kebutuhan rakyat sehari-hari.
Dalam kajian ilmu politik, kemenangan besar seperti yang diraih oleh kubu Prabowo-Gibran bisa dikategorikan sebagai bentuk konsolidasi kekuasaan ideologis yang berhasil. Aliansi besar lintas partai yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PSI membentuk blok kekuatan yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga lentur dalam menyerap berbagai aspirasi publik. Mereka berhasil membungkus narasi kebangsaan dalam bingkai populisme digital: kampanye meme, gaya komunikatif Gibran, serta sentuhan media sosial yang menyasar generasi muda menjadi penentu kemenangan.
Keberhasilan pasangan ini menembus wilayah mayoritas non-Muslim seperti NTT dan Papua menunjukkan bahwa nasionalisme versi baru yang ditawarkan cukup inklusif dan diterima lintas segmen. Hal ini kontras dengan narasi Islamisme politik yang cenderung tertutup dan gagal membangun jembatan narasi yang kohesif untuk konteks multikultural Indonesia.
Kelompok Islam politik tidak pernah benar-benar absen dari panggung politik Indonesia. Namun pada Pemilu 2024, peran mereka justru terlihat melemah. Meskipun partai-partai Islam seperti PKS, PKB, PAN, dan PPP tetap bertahan di parlemen, mereka gagal membangun poros yang solid. Fragmentasi identitas antara PKB yang berbasis NU, PAN yang dekat dengan Muhammadiyah, dan PKS yang berakar dari Tarbiyah menghambat terciptanya agenda bersama. Bahkan PPP, partai Islam tertua, terancam tak lolos ambang batas parlemen secara nasional dengan perolehan sekitar 3,9%.
Di ranah pilpres, pasangan Anies-Muhaimin sebenarnya menjadi satu-satunya poros yang bisa dikategorikan sebagai Islamis-moderat. Namun, mereka tidak berhasil merebut dukungan luas di luar basis loyal tradisional. Ini menunjukkan bahwa pendekatan identitas berbasis agama belum cukup untuk menjadi kekuatan utama tanpa dibarengi agenda ekonomi dan sosial yang konkret dan inklusif.
Provinsi Lampung menjadi cermin menarik dari peta nasional. Berdasarkan hasil pemilu legislatif DPRD Provinsi Lampung 2024, partai-partai nasionalis seperti Gerindra, PDIP, dan Golkar mendominasi. Gerindra menempati posisi pertama dengan lebih dari 700 ribu suara, diikuti PDIP dan Golkar. PKB memang memperlihatkan kekuatan lokal di kabupaten seperti Lampung Timur dan Tulang Bawang Barat, tetapi tidak dibarengi dengan sinergi oleh partai Islam lainnya. PKS dan PAN harus puas di posisi tengah, sementara PPP bahkan tak mendapat kursi di DPRD Provinsi.
Situasi ini diperparah oleh dominasi politik berbasis figur dan patronase lokal. Di beberapa kabupaten/kota, partai kecil seperti Partai Buruh dan Hanura masih bisa merebut kursi berkat tokoh lokal yang kuat dan jaringan sosial yang solid. Ini memperlihatkan bahwa dalam konteks lokal, ideologi sering kali bukan faktor utama; kedekatan, koneksi, dan pragmatisme lebih menentukan pilihan pemilih.
Salah satu fenomena penting yang juga muncul adalah menguatnya peran figur politik dalam mendongkrak suara. Prabowo dan Gibran bukan hanya pasangan kandidat, tetapi juga ikon dalam lanskap politik digital. Gaya komunikasi santai, pendekatan humoris, dan narasi kerakyatan yang terus digaungkan di media sosial memberi efek resonansi tinggi, khususnya di kalangan pemilih muda (Gen Z dan milenial) yang jumlahnya mencapai lebih dari 56% pemilih nasional.
Dalam konteks ini, partai Islam gagal menampilkan figur muda yang menonjol dan mampu bergaul dengan dunia digital. Tidak ada “juru bicara politik Islam” yang karismatik dan relevan dengan wacana anak muda. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi partai Islam bila ingin tetap relevan dalam pemilu 2029.
Dominasi kekuatan nasionalis dalam Pemilu 2024 tidak berarti tanpa tantangan. Koalisi besar yang terbentuk pasca pemilu harus diuji dalam tata kelola pemerintahan ke depan. Publik menunggu apakah narasi inklusif dan populis yang dikampanyekan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Sementara itu, kelompok Islamis perlu mengevaluasi ulang strategi mereka. Bukan hanya soal koalisi teknis, tetapi juga soal cara berkomunikasi, relevansi isu, serta pendekatan ke generasi muda dan pemilih perkotaan. Jika tidak, maka mereka hanya akan menjadi pelengkap kekuasaan, bukan poros utama seperti yang pernah dicita-citakan era reformasi dulu.
Peta politik 2024 memberi pelajaran bahwa rakyat Indonesia semakin rasional, pragmatis, dan digital. Mereka mencari representasi yang mampu memahami bahasa zaman, bukan sekadar jargon ideologi lama. Nasionalisme yang lentur, inklusif, dan modern menang telak. Islamisme politik harus berbenah dan belajar memahami bahwa pemilih masa kini menuntut lebih dari sekadar identitas.