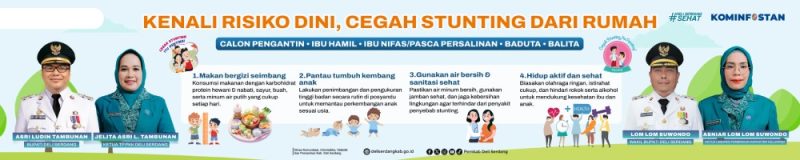Oleh Christian Saputro penyuka sejarah.
Menjelang sore di Gedung Oudetrap, Kota Lama Semarang, udara membawa aroma campuran antara sejarah dan percakapan yang hangat. Bangunan tua berarsitektur kolonial itu menjadi saksi bagi sebuah perjumpaan yang tak sekadar membicarakan masa lalu, tetapi juga merajut masa depan — Diskusi Budaya Peranakan dalam rangkaian Festival Bubak Semarang 2025.
Kursi-kursi tua tersusun rapi. Sekitar lima puluh orang hadir, mulai dari peneliti, pegiat budaya, jurnalis, hingga warga yang datang dengan rasa ingin tahu. Mereka berkumpul di bawah cahaya lampu kuning yang jatuh lembut ke dinding bertekstur tua, seolah mengajak semua yang hadir untuk menyelam lebih dalam ke kisah-kisah yang telah ratusan tahun membentuk wajah Semarang.
Tema yang diangkat sore itu: “Festival Cheng Ho: Warisan Budaya Peranakan dalam Tradisi Multikultural di Semarang”. Bagi sebagian orang, nama Cheng Ho memanggil ingatan pada kisah pelayaran besar dari Tiongkok yang menembus samudra. Namun bagi warga Semarang, nama itu juga melekat pada Arak-Arakan Jaran Sampo — kirab yang setiap tahun membawa patung Dewa dari Klenteng Tay Kak Sie di Pecinan menuju Sam Poo Kong, diikuti ribuan langkah yang berpadu dalam satu irama.
Yvonne Sibuea, peneliti dari Ein Institute, memulai dengan mengurai asal-usul arak-arakan ini. Ia bercerita tentang bagaimana tradisi ini lahir, bertahan, dan berkembang menjadi perayaan multikultural, di mana warna merah lampion berpadu dengan gamelan, dan aroma dupa bersisian dengan wangi bunga melati.
Lalu Foe Jose Amadeus, seorang pegiat budaya Tionghoa, mengajak hadirin menengok makna festival ini dari dalam. Baginya, Festival Cheng Ho bukan sekadar ritual, melainkan pengikat identitas bagi komunitas Tionghoa-Peranakan di Semarang. Ia mengingatkan, tantangan terbesar bukanlah menjaga formasi kirab, melainkan menyalakan semangat di hati generasi muda agar tradisi tak berhenti di sini.
Sementara itu, Johannes Christiono, jurnalis yang bertahun-tahun merekam festival ini lewat lensa kameranya, menghadirkan fragmen-fragmen visual: anak-anak yang tersenyum di pinggir jalan, kakek-nenek yang duduk di kursi plastik sambil melambaikan tangan, hingga deretan barongsai yang bergerak lincah di antara kerumunan. Ia mencatat, meski ada penyesuaian di sana-sini, ruh kebersamaan lintas budaya selalu pulang ke festival ini.
Diskusi sore itu ditutup dengan refleksi yang mengikat semua cerita: bahwa warisan budaya peranakan adalah milik bersama. Ia bukan milik satu etnis, satu agama, atau satu generasi saja, melainkan sulaman panjang yang menenun Tionghoa, Jawa, Arab, dan Eropa menjadi kain besar bernama Semarang.
Di luar gedung, matahari telah merunduk di balik atap-atap tua Kota Lama. Sinar oranye menyapu jalanan berbatu, seakan ikut merestui percakapan yang baru saja terjadi. Bubak — membuka — bukan hanya berarti menghidupkan kembali ruang publik, tetapi juga membuka hati untuk menerima bahwa keberagaman adalah harta yang paling layak dirayakan. (*)