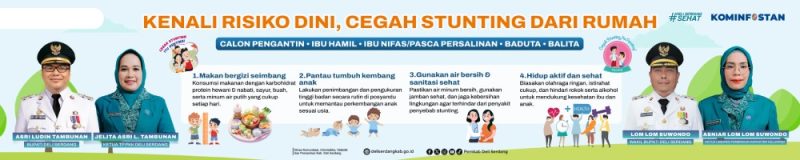Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Sumatera Post tinggal di Semarang.
Jakarta, Oktober 2025. Di bawah gemerlap lampu Tri Brata Convention Center, gema tepuk tangan menggema usai palu sidang diketuk untuk terakhir kalinya. Sidang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2025 resmi ditutup dengan keputusan monumental: 514 karya budaya dari berbagai pelosok Nusantara kini resmi menyandang predikat Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI).
Sebuah momen yang lebih dari sekadar seremoni—ini adalah pernyataan cinta negara kepada jati diri bangsanya sendiri. Dengan penetapan terbaru ini, tercatat sudah 2.727 WBTbI yang diakui hingga tahun 2025. Di balik angka itu, tersimpan napas, doa, dan kisah panjang ribuan komunitas budaya yang terus berjuang melawan arus zaman.
Semarang: Kota yang Hidup dari Napas Tradisi
Dari jantung Jawa Tengah, Kota Semarang menorehkan langkah pasti. Di bawah kepemimpinan dan dedikasi para pelaku budayanya, 17 karya budaya kini telah sah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Mulai dari Dugderan, pesta rakyat penuh warna yang menandai datangnya Ramadan, hingga Warak Ngendog, simbol harmoni etnis dan kepercayaan. Dari aroma Lunpia Semarang yang melegenda, hingga Macapat Semarangan yang lirih tapi menggetarkan jiwa.
Kota ini tak hanya menjaga masa lalunya—ia menghidupkan kembali roh budaya di tengah denyut modernitas. “Setiap penetapan bukan sekadar penghargaan administratif,” tutur Haryadi Dwi Prasetyo. “Ini adalah pengakuan bahwa budaya kita masih hidup, masih berdenyut, dan masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.”
Makna Sebuah Pengakuan
Penetapan WBTbI bukanlah akhir, melainkan pijakan awal. Ia menjadi dasar bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.
Dengan perlindungan, tradisi tak lagi sekadar cerita lisan yang mudah terhapus waktu—ia tercatat, terdokumentasi, dan memiliki payung hukum yang kuat.
Sementara itu, pengembangan dan pembinaan memberi ruang bagi generasi muda untuk menafsirkan ulang tradisi dengan semangat kekinian. Di tangan mereka, gambang semarang bisa berdialog dengan musik elektronik; batik asem semarangan bisa hadir dalam panggung mode dunia; dan wayang potehi bisa dinikmati dalam kemasan visual baru tanpa kehilangan ruhnya.
Tantangan dan Tanggung Jawab
Namun menjaga budaya bukan perkara mudah. Di tengah derasnya arus globalisasi, budaya tradisional kerap terpinggirkan oleh pesona instan dunia digital. Tantangan kini bukan lagi sekadar melestarikan, melainkan memastikan warisan itu tetap relevan.
Di sinilah tugas besar generasi muda: menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Mereka bukan sekadar pewaris, tetapi juga penafsir baru kebudayaan. Mereka harus berani menulis ulang narasi tradisi, tanpa menghapus nilai yang diwariskan leluhur.
Lestari Budayaku, Teguh Identitasku
Warisan budaya bukan sekadar benda atau perayaan—ia adalah denyut kehidupan, bahasa batin yang meneguhkan siapa kita. Setiap warak, lunpia, macapat, dan dugderan adalah simbol bahwa Semarang, dan Indonesia pada umumnya, masih memiliki akar yang kuat di tengah perubahan zaman.
“Menjaga budaya adalah menjaga jati diri bangsa,” pungkas Haryadi. “Dan ketika kita melestarikan budaya, sejatinya kita sedang melestarikan kemanusiaan kita sendiri.” Ujar Haryadi. (*)