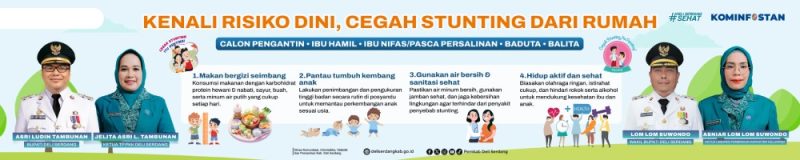Oleh: Esti Aryani, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Hukum yang Menghukum Terlalu Banyak
Dalam sistem peradilan pidana, penjara selalu disebut sebagai simbol terakhir dari keadilan: dimana tempat orang yang bersalah menebus dosanya. Namun, di Indonesia, penjara justru sering menjadi simbol kegagalan hukum. Dengan tingkat overkapasitas mencapai lebih dari 200 persen di sebagian besar lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), fungsi pemasyarakatan kini telah bergeser menjadi sekadar “penyimpanan manusia.”
Di balik jeruji, ribuan narapidana hidup dalam kondisi yang tidak layak, ruang sel berisi 20 hingga 30 orang, sanitasi buruk, makanan terbatas, dan fasilitas kesehatan minim. Negara seolah lupa bahwa setiap orang, termasuk terpidana, tetap memiliki martabat dan hak asasi manusia. Hukum boleh menghukum, tapi tidak boleh mendiskriminasi kemanusiaan.
Overkapasitas sebagai Cermin Krisis Hukum
Fenomena overkapasitas bukan hanya masalah fisik, tetapi masalah sistemik. Ini mencerminkan betapa hukum pidana kita masih terlalu mudah memenjarakan orang, bahkan untuk pelanggaran ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pidana lain lebih sering menumpuk sanksi kurungan daripada mengedepankan sanksi alternatif seperti denda, kerja sosial, atau pidana pengawasan.
Sebagian besar penghuni penjara di Indonesia adalah pelaku tindak pidana ringan dan pengguna narkotika. Mereka bukan pelaku kekerasan atau korupsi besar, melainkan warga biasa yang terjebak dalam sistem hukum yang kaku dan tidak proporsional. Ironisnya, ketika penjara penuh oleh pelaku kecil, pelaku besar justru mudah mendapatkan keringanan, penundaan, atau grasi. Sistem yang seperti ini bukan hanya tidak efisien, tetapi juga tidak adil. Negara justru menghabiskan anggaran besar untuk memelihara sistem yang menghasilkan penderitaan, bukan perbaikan.
Hak Asasi Manusia yang Tersandera
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G dan 28I UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi. Jaminan itu ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia.
Namun, realitas di balik tembok lapas sering kali bertolak belakang. Kelebihan kapasitas hingga tiga kali lipat menyebabkan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Banyak narapidana tidur berdesakan, bergantian tempat istirahat, dan tidak mendapat layanan kesehatan memadai. Kondisi itu bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi pelanggaran HAM struktural. Ketika negara gagal menjamin hak-hak dasar narapidana, maka yang bersalah bukan lagi individu pelaku kejahatan, melainkan sistem hukum yang tidak manusiawi.
Dari Penjara ke Pemasyarakatan: Konsep yang Terlupakan
Filosofi dasar sistem pemasyarakatan Indonesia sebenarnya indah: Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat balas dendam, tetapi tempat rehabilitasi dan pembinaan. Tujuannya bukan menghancurkan, melainkan mengembalikan warga binaan agar dapat diterima kembali di masyarakat. Namun, cita-cita itu kini hanya menjadi jargon di papan nama gedung. Bagaimana mungkin pembinaan berjalan jika satu petugas harus mengawasi ratusan tahanan, dan ruang pembinaan lebih sempit daripada sel penahanan? Bagaimana mungkin rehabilitasi terjadi jika sistem hukum kita lebih sibuk menjebloskan orang daripada mencegah kejahatan? Penjara yang sesak tidak hanya gagal membina, tetapi juga menciptakan lingkaran kejahatan baru. Banyak mantan narapidana keluar dengan kondisi lebih buruk yaitu kehilangan harga diri, pekerjaan, dan kesempatan sosial, lalu kembali ke dunia kriminal sebagai satu-satunya pilihan hidup yang tersisa.
Solusi: Dari Reformasi Pidana ke Kemanusiaan
Krisis overkapasitas tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun penjara baru.
Masalah ini membutuhkan reformasi paradigma hukum pidana. Pertama, negara harus mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara. Tindak pidana ringan, terutama terkait ekonomi kecil atau pelanggaran administratif, seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme denda, mediasi penal, atau keadilan restoratif. Pendekatan seperti ini sudah diterapkan di banyak negara dan terbukti menekan angka penghuni penjara tanpa mengurangi efek jera. Kedua, perlu diterapkan seleksi rasional terhadap tahanan pra-peradilan. Banyak tahanan belum divonis, tetapi sudah mendekam berbulan-bulan di rutan karena proses peradilan lambat atau jaminan penangguhan sulit didapat.
Padahal asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) mewajibkan negara untuk tidak memperlakukan mereka seperti narapidana. Ketiga, reorientasi lembaga pemasyarakatan ke arah rehabilitasi nyata. Lapas harus kembali menjadi lembaga pendidikan sosial dan keterampilan, bukan sekadar tempat menunggu waktu. Kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga sosial perlu diperkuat agar warga binaan dapat belajar keterampilan yang relevan dan mendapatkan peluang setelah bebas. Keempat, pengawasan independen dari Komnas HAM dan Ombudsman harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran di dalam lapas. Keterbukaan data, audit fasilitas, dan pelaporan publik harus menjadi kewajiban, bukan pilihan.
Penutup: Mengembalikan Kemanusiaan ke Dalam Hukum
Hukum pidana yang baik bukan diukur dari seberapa banyak orang yang dipenjara, tetapi dari seberapa banyak manusia yang diselamatkan. Overkapasitas dan kondisi penjara yang tidak manusiawi adalah bukti bahwa sistem kita sedang kehilangan arah moralnya. Negara yang beradab tidak membiarkan keadilan berubah menjadi penyiksaan yang dilegalkan. Keadilan sejati adalah ketika hukum menghukum dengan rasa kemanusiaan. Sebab di balik setiap narapidana, masih ada manusia dan di balik setiap jeruji, masih ada hak asasi yang harus dijaga. Menjaga mereka bukan berarti membenarkan kejahatan, tetapi menegakkan kemanusiaan dalam hukum. Dan di situlah ukuran sejati dari peradaban hukum sebuah bangsa.