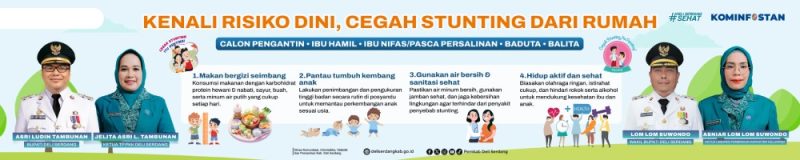Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro, Jurnalis, pencacat peristiwa tinggal di Tembalang Semarang.
Malam itu, langit Semarang menggantung rendah, seolah ikut menunduk menyambut nyanyian yang tak sekadar lantang, tapi juga lembut dan penuh harap. Di jantung kota, di sebuah bangunan gereja tua di Karangsaru, ruang ibadah berubah rupa. Bukan mimbar semata, tapi panggung kebangsaan—tempat perbedaan berpaut mesra dalam nada, tempat keyakinan berpadu dalam puisi dan nyanyian.
GKI Karangsaru, Jumat malam (1/8/2025), menjadi tuan rumah bagi sebuah peristiwa yang tak biasa namun sangat Indonesia: “Harmoni Gita Anak Bangsa”. Sebuah konser kebangsaan, namun lebih dari sekadar konser. Ia adalah ziarah kebangsaan—ziarah rasa, ziarah jiwa.
Digagas oleh kolaborasi lintas lembaga dan lintas iman—Pelita, EIN Institute, Klub Merby, EduHouse, serta Rotary Club of Semarang Bimasena, konser ini menjadi titik temu antara keberagaman dan kebersamaan. Sejenak, Indonesia tak lagi berwajah tegang atau curiga, tapi bersenyum dalam perbedaan.
 “Konser ini adalah cermin dari cita-cita Indonesia merdeka,” ujar Ellen Nugroho, Direktur Eksekutif EIN Institute. “Karena meski sudah delapan dekade merdeka, pekerjaan rumah kita masih banyak, terutama dalam merobohkan sekat-sekat yang memisahkan.”
“Konser ini adalah cermin dari cita-cita Indonesia merdeka,” ujar Ellen Nugroho, Direktur Eksekutif EIN Institute. “Karena meski sudah delapan dekade merdeka, pekerjaan rumah kita masih banyak, terutama dalam merobohkan sekat-sekat yang memisahkan.”
Wajah Indonesia: Nyata dan Penuh Warna
Lima ratus orang hadir malam itu, tak satu pun seragam. Yang ada hanyalah keberagaman yang membaur. Di kursi yang sama duduk bhikkhu berdampingan dengan biarawati. Di belakang mereka, tokoh Konghucu mengenakan jubah panjang, duduk bersisian dengan penghayat kepercayaan yang berbalut kebaya dan ikat kepala. Tak ada jarak. Tak ada kecurigaan. Yang ada hanya simpul-simpul persaudaraan yang ditautkan oleh nada dan hati.
Lagu-lagu kebangsaan mengalun seperti doa: Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Rayuan Pulau Kelapa, Syukur. Tapi kali ini bukan dinyanyikan dalam upacara resmi. Ia dinyanyikan dengan penuh kesadaran, dari dada yang jujur, dari cinta yang sudah letih menanti Indonesia yang ramah pada semua anaknya.
Mengiringi lantunan itu, berdentanglah orgel pipa kayu dan bambu—buatan tangan-tangan muda Semarang. Satu-satunya organ pipa aktif di kota ini, dengan lebih dari seribu pipa menyuarakan kebhinekaan secara harfiah. Kolintang, terompet, dan akhirnya… angklung dimainkan bersama oleh semua hadirin. Suara menjadi jembatan. Bambu menjadi lambang. Musik menjadi bahasa paling universal.
Ketika Kata Menjadi Pelita
Tak hanya nada, malam itu juga digemakan oleh kata-kata yang menyalakan makna. Puisi-puisi dibacakan dengan khidmat dan cinta oleh para tokoh lintas iman: Gus Fadel Irawan (Islam), Bhikkhu Ditthisampano Mahathera (Buddha),Sr. Yulia SDP (Katolik), dr. Komang Dipta Januraga (Hindu), Ws. Andi Gunawan (Konghucu), Samuel Wattimena (Kristen), Ruwiyati (Penghayat Kepercayaan)
Kata-kata mereka bukan ceramah, melainkan pelita—menembus kabut prasangka, menyiramkan hangat ke tanah yang mulai retak oleh politik identitas dan kepentingan sesaat.
Anak Muda dan Masa Depan yang Tak Menunggu
Tiga anak muda Semarang turut berbicara.
Mereka bukan orator, tapi pelaku sejarah masa kini: Falasifah, inovator bioteknologi, Reza Kurniawan, pejuang hak disabilitas , Gemma Tedjokusumo, penggerak ruang kreatif
Mereka membuktikan bahwa generasi muda bukan hanya penerus, tapi juga penentu. Mereka tidak menunggu panggung diberikan. Mereka menciptakan panggungnya sendiri—dengan karya, dengan tekad, dengan kepedulian.
“Masyarakat butuh ruang yang jujur dan menyentuh. Bukan seremoni, tapi tempat di mana kita bisa hadir sebagai manusia,” kata Setyawan Budy dari Pelita.
“Musik menyatukan, bukan memisahkan,” ujar Linggayani Soentoro, Presiden Rotary Club Semarang Bimasena.
“Dan orgel bambu ini,” tambah Krisna Phiyastika dari Klub Merby, “adalah wujud cinta tanah air. Dibuat oleh anak bangsa, untuk menyuarakan suara Indonesia.”
Dari Panggung Ini, Untuk Panggung yang Lebih Besar
Panggung malam itu bukan hanya milik para penyanyi atau tokoh. Ia adalah cermin dari panggung yang lebih besar: Kota Semarang. Dan panggung itu, kita jaga bersama agar tetap menjadi tempat pentas keberagaman dan keadilan, bukan direbut oleh mereka yang alergi pada perbedaan.
Sebelum acara ditutup, dua suara emas—dr. Edward Tirtananda dan Marsha Marianne—menyanyikan lagu yang membuat banyak mata basah. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena di tengah berita duka dan kegaduhan bangsa, malam itu menjadi oase—di mana cinta pada tanah air terasa nyata dan bisa dipegang.
Dan dari tengah hadirin, teriak bergema:
“Harmoni Gita Anak Bangsa!”
“Merajut harmoni, memupus prasangka!”
Epilog: Tentang Cinta yang Tak Bisa Pergi
Seorang peserta membisikkan kesannya, “Rasanya seperti film Sore yang viral itu… lelah berharap pada negeri ini, tapi tak bisa berhenti mencintainya.”
Dan mungkin, itulah esensi dari Harmoni Gita Anak Bangsa.
Ia bukan pesta. Ia bukan upacara. Ia adalah cara kita berkata:
Kami masih percaya. Kami masih mencintai.Dan kami ingin Indonesia tetap jadi rumah —bagi semua (*)