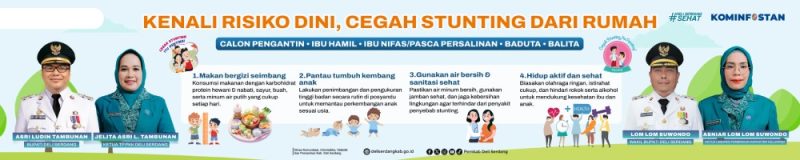Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Sumatera Post tinggal di Semarang
Di halaman Gedung beratap limasan yang sudah berumur hampir satu abad, denting gamelan kembali bergetar, menembus dinding waktu. Sabtu malam itu, Gedung Sobokartti, yang berdiri teguh di Jalan Dr. Cipto Nomor 31 Semarang sejak tahun 1929, berubah menjadi samudra seni. Riuh tepuk tangan, sorak, dan gelegar kendang berpadu jadi satu. Malam itu, panggung sakral kebudayaan ini merayakan ulang tahunnya yang ke-96 dengan persembahan spektakuler bertajuk “Satu Panggung Tiga Jiwa”.
Sebuah tajuk yang bukan sekadar retorika, tapi benar-benar hidup di panggung—karena dalam satu tarikan napas, tiga bentuk seni wayang menyatu: Wayang Orang (Dance Theater), Wayang Kulit Purwa (Tradisi), dan Wayang Sandosa (Kontemporer). Mereka berpadu dalam satu lakon yang agung dan berlapis makna: “Pandowo Timbul.”
 Tiga Jiwa dalam Satu Tubuh Seni
Tiga Jiwa dalam Satu Tubuh Seni
Pertunjukan ini seperti menghidupkan kembali ruh Sobokartti itu sendiri—tempat di mana tradisi, pendidikan, dan kebudayaan berpadu. Dalam kolaborasi ini, setiap medium wayang menjadi “jiwa” yang berbeda: Wayang Orang menghadirkan tubuh dan gerak, Wayang Kulit memancarkan bayang dan suara tradisi, sementara Wayang Sandosa menjadi percikan imajinasi masa kini.
Disutradarai oleh Paminto Krisna, “Pandowo Timbul” menjadi panggung tempat sejarah dan kontemporer berdialog, bukan bertarung. Sembilan dalang muda dari komunitas To Be Confirm (TBC) tampil dengan semangat eksperimental—Daniel Dwi Saputra, Rendy Octavianto, Cahyaning Jagad Bilowo Jati, Galih Aryaputra Harfansyah, Irfan Dao Zaidan Nabhan, Yanuar Finsa Setiano, Mohammad Asy’Aril, M. Farhan Alfawwaz, dan Andro Wakawimbang—mengisi ruang antara klasik dan kini, antara kitab dan kenyataan.
Sementara Ki Yusuf Anom Suwito, dalang wayang kulit yang matang dalam pakem, menghadirkan suara tradisi yang dalam—ditemani dua sinden: Diyah dan Umi. Di belakang mereka, para pengrawit muda mengalirkan energi tak henti: nama-nama yang barangkali belum sepopuler maestro, tetapi malam itu, mereka menyalakan bara masa depan kesenian Jawa. Sebut saja, Tantya Widigdya, Nuril Absori, Muhammad Nur Roosyid, M. Fiorello Falah, Angger Sabda danadyaksa, Raken galih maheikal, Argy Alfaresya, Vanes Sandy Yudha, Fajar Adhsa Fransetya, Eko Prasetyo Shri Dananjaya, Kuncoro Bayu Utomo, Ardhiansyah putra maulana, Erwin Dwi Kurniawan, Bayu Tri Murdoko, Dimas Satria Pamenang, Badiva Lanank Aldani, Alfy Rifqifathony, Isfadhil Kholifatul Anwar L. T, Bimo Adi Saputro dan Dananto Purbiyatmono.
Pandowo Timbul: Kisah yang Menyentuh Zaman
“Pandowo Timbul” bukan sekadar kisah kebangkitan Pandawa dari pengasingan. Ia adalah cermin dari kehidupan manusia yang jatuh dan bangkit kembali. Para Pandawa—Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa—dihadirkan bukan hanya sebagai tokoh mitologi, tapi sebagai lambang dari manusia modern yang berjuang melawan keputusasaan, godaan kekuasaan, dan kelelahan nurani.
Bima bertarung dengan amarahnya, Arjuna dengan godaan hatinya, Yudhistira dengan kebimbangannya. Dan di antara mereka, Semar dan punakawan menjadi suara nurani—suara rakyat yang sederhana namun bijak, yang sering dilupakan ketika dunia terlalu sibuk mengejar kejayaan.
Dalam tafsir Paminto Krisna, lakon ini bukan sekadar “tontonan”, tetapi “tuntunan batin.” “Kita sering melihat ketidakadilan, pelecehan, dan kezaliman, tapi hanya berani menonton tanpa bertindak,” katanya lirih usai pertunjukan. “Lewat ‘Pandowo Timbul’, saya ingin mengajak penonton untuk menengok ke dalam diri sendiri. ‘Timbul’ bukan hanya bangkit dari tanah, tapi bangkit dari kesadaran.”
Refleksi itu menggema ke seluruh ruang. Seolah Sobokartti sendiri, setelah 96 tahun berdiri, juga sedang “timbul” kembali—bangkit dari masa ke masa, dari generasi ke generasi.
Sobokartti: Rumah yang Tak Pernah Sepi Jiwa
Sejarah mencatat, Gedung Sobokartti dibangun oleh R.M. Joesoep Hadikoesoemo pada tahun 1929, dengan rancangan arsitek besar Thomas Karsten. Sejak awal, ia bukan sekadar gedung pertunjukan, melainkan ruang pendidikan karakter melalui seni. Dari sinilah lahir seniman, guru, dan pelaku kebudayaan yang menjadikan Semarang tak pernah kehilangan denyut seninya.
Kini, di usianya yang ke-96, Sobokartti tetap menjadi “cagar budaya yang bernyawa.” Ia bukan sekadar monumen masa lalu, melainkan panggung yang terus dihidupi—oleh wayang, tari, gamelan, dan oleh semangat anak muda yang mencintai tanah air melalui kesenian.
Menutup Waktu, Membuka Makna
Malam semakin larut. Cahaya lampu menimpa wajah para penonton yang masih terpaku. Gamelan terakhir mengalun pelan, seperti doa yang disampaikan lewat nada. Sobokartti kembali hening, tapi bukan hening yang mati—melainkan hening yang menyimpan gema, gema 96 tahun perjalanan seni dan kebudayaan di jantung Kota Semarang.
“Pandowo Timbul” pun berakhir, tapi maknanya masih berputar di dada: bahwa dalam setiap kejatuhan, selalu ada kemungkinan untuk bangkit dan tegak kembali (*)