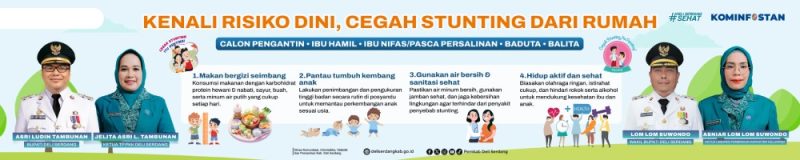Oleh: Mukhlisin
Jakarta – Panas mentari pagi menelusuk kulit saat Rudi melangkah pelan di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Ia tukang ojek pangkalan yang telah belasan tahun mencari nafkah di antara riuh kemacetan ibu kota. Pagi itu, ia harus berjalan lebih jauh dari biasanya—trotoar tempat ia biasa menunggu penumpang tengah diperbaiki, lagi.
“Setiap lima tahun ganti trotoar. Tapi buat kami, yang penting nanti masih boleh duduk di sini atau tidak,” ucapnya lirih, dengan senyum pahit.
Kalimat sederhana itu mungkin akan terlupakan, namun bagi saya, ia membuka mata akan sisi lain Jakarta: bukan hanya kota megah dengan pencakar langit, MRT, dan pusat ekonomi, tetapi juga rumah rapuh bagi mereka yang menggantungkan hidup pada denyut kota yang sering kali tak bersahabat.
Kota yang Tak Tidur, Tapi Selalu Letih
Jakarta terus berubah. Tiap hari, proyek baru digulirkan—jalan tol layang, fase baru MRT, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), hingga rencana reklamasi. Di atas kertas, ini semua demi kemajuan kota: lebih cepat, efisien, dan modern.
Namun kenyataan di lapangan jauh lebih rumit.
Ketika segelintir elite menikmati apartemen mewah dan transportasi cepat, warga miskin kota harus rela kehilangan tanah, air bersih, bahkan hak dasar untuk tinggal layak karena penataan ruang yang tidak berpihak.
Di Kampung Akuarium, trauma penggusuran masih membekas. Di Marunda, laut yang dulu menopang hidup nelayan kini tercemar limbah. Di tengah riuhnya mesin pembangunan, suara mereka tenggelam oleh gemuruh alat berat dan kebijakan yang tak mendengar.
MRT dan Harapan yang Belum Sampai
Kehadiran MRT adalah tonggak sejarah. Dari Bundaran HI ke Lebak Bulus, kereta ini mengubah cara warga bergerak. Namun, keberadaannya juga menyingkap ketimpangan yang nyata: tiket memang terjangkau, tapi akses untuk penyandang disabilitas dan warga marjinal masih terbatas.
Lebih dari itu, wilayah pinggiran—tempat sebagian besar warga bermukim—belum tersentuh jalur ini. Mereka masih bertumpu pada angkot tua atau bus yang tak selalu pasti.
MRT adalah simbol kemajuan. Tapi bagi sebagian besar warga, kemajuan itu belum berhenti di stasiun mereka.
Jakarta dan Banjir yang Tak Pernah Absen
Musim hujan datang, dan banjir seperti ritual tahunan. Jalanan tergenang, rumah-rumah kebanjiran, dan warga waswas menanti listrik padam.
Namun banjir bukan sekadar urusan hujan. Ia adalah cermin dari pengelolaan kota yang rapuh—drainase tak terurus, sungai dijadikan jalan, dan ruang hijau menyusut oleh beton yang terus menjalar.
Proyek besar seperti Giant Sea Wall dan sodetan Ciliwung menjanjikan solusi, namun hingga kini, semuanya masih sebatas rencana di atas meja.
Dan lagi-lagi, yang paling menderita adalah mereka yang tinggal di tepian: di kolong jalan tol, di bantaran kali—mereka yang hidupnya selalu berada di antara risiko dan pengusiran.
Membangun Jakarta Bukan Sekadar Membangun Gedung
Jakarta butuh pembangunan, itu tak terbantahkan. Tapi lebih dari itu, Jakarta perlu pembangunan yang manusiawi.
Kita memerlukan kebijakan yang tak hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga menumbuhkan keadilan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Perlu pemimpin yang tak sekadar bicara di podium, tetapi juga berani hadir dan mendengar mereka yang tersisih.
Jakarta Adalah Kita Semua
Jakarta adalah wajah dari impian dan kegagalan kita sebagai bangsa. Di sini, masa depan Indonesia dipertaruhkan.
Jika kita sungguh ingin Jakarta menjadi kota yang berkelanjutan, maka pembangunannya harus dimulai dari rasa: dari hati, dari empati. Kota ini harus bisa memberi ruang bagi semua: dari investor sampai nelayan, dari direktur hingga tukang ojek.
Karena Jakarta bukan sekadar beton dan gedung tinggi.
Jakarta adalah manusia yang menghidupinya.
Dan hanya dengan mendengar denyut hati mereka, Jakarta bisa bertahan—dan tumbuh.(*)