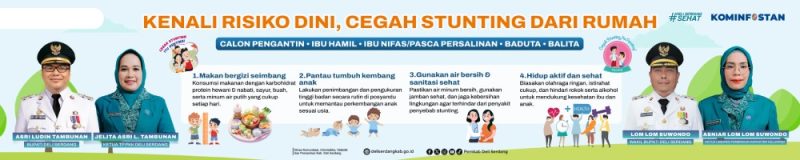Nur Fadhilah, M. Kes, Ph. D
Dosen Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung
Sumaterapost.co | Pringsewu – Tuberkulosis (TBC) bukan hanya masalah infeksi paru, tetapi juga luka sosial yang terus menganga dalam diam. Di balik data morbiditas dan mortalitas yang kerap kita baca dalam laporan epidemiologi, tersembunyi ribuan kisah manusia yang terpenjara oleh satu kata: “STIGMA”. Hingga hari ini, stigma terhadap orang dengan TBC tetap menjadi salah satu tantangan paling serius dalam pengendalian penyakit ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Stigma ini beroperasi diam-diam, namun dampaknya menghancurkan: menyulitkan deteksi dini, menghambat pengobatan, dan memperburuk kualitas hidup pasien.
Indonesia saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus tuberkulosis (TBC). Berdasarkan laporan Global Tuberculosis Report 2023 dari WHO, diperkirakan terdapat sekitar 1.060.000 kasus baru TBC di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan beban besar penyakit TBC di tengah masyarakat Indonesia. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah sekitar 30% dari jumlah kasus tersebut tidak ditemukan atau tidak dilaporkan. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian dan eliminasi TBC secara nasional. Banyak kasus yang tidak tercatat karena penderita enggan memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Rasa takut terhadap diskriminasi dan penolakan sosial menjadi penyebab utama mengapa banyak penderita menyembunyikan penyakitnya. Selain itu, rasa malu yang muncul akibat stigma masyarakat terhadap TBC memperburuk situasi. Padahal, TBC merupakan penyakit yang bisa disembuhkan jika didiagnosis dan diobati secara tepat. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menghapus stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini dan pengobatan TBC.
Stigma terhadap penderita TBC merupakan bentuk kekejaman sosial yang masih sering terjadi di masyarakat. Stigma ini tidak hanya menyebabkan penderita dikucilkan, tetapi juga membungkam suara dan hak mereka untuk mendapatkan perawatan yang layak. Banyak orang yang takut untuk diketahui mengidap TBC karena khawatir dijauhi oleh keluarga, teman, atau rekan kerja. Akibatnya, mereka cenderung menunda pemeriksaan kesehatan meskipun sudah merasakan gejala. Tidak sedikit pula yang enggan minum obat secara rutin karena takut diagnosisnya terbongkar. Bahkan, beberapa penderita memilih untuk menyembunyikan kondisi mereka dari orang-orang terdekat. Dalam situasi seperti ini, stigma menjadi lebih dari sekadar persoalan sosial; ia telah berubah menjadi hambatan besar dalam upaya pengendalian TBC. Maka, menghapus stigma adalah langkah krusial dalam mendukung deteksi dini, pengobatan tuntas, dan pemutusan rantai penularan TBC.
Faktanya, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan, dan pengobatannya tersedia secara gratis melalui layanan kesehatan primer. Namun, stigma membuat informasi ini tidak berdaya. Orang lebih takut dijauhi daripada sakit itu sendiri. Lebih takut dikucilkan daripada batuk berkepanjangan. Lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan nyawa. Kementerian Kesehatan RI dan WHO telah menetapkan strategi penanggulangan TBC yang berfokus pada skrining aktif, deteksi dini, pengobatan tuntas, dan perluasan terapi pencegahan TBC (TPT). Tapi pertanyaannya: bagaimana strategi ini akan berjalan optimal jika masyarakat sendiri masih memandang penderita TBC sebagai “ancaman” sosial? Di sinilah letak paradoksnya. Kita ingin mengakhiri TBC, tetapi tanpa mengakhiri stigma, semua upaya bisa menjadi sia-sia.
Stigma tumbuh subur di lahan ketidaktahuan dan miskonsepsi. Banyak yang masih percaya bahwa TBC adalah penyakit kutukan, akibat gaya hidup kotor, atau penyakit keturunan. Semua anggapan itu tidak benar. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, ditularkan melalui udara, dan dapat menginfeksi siapa saja, tanpa memandang status ekonomi, pendidikan, maupun moralitas. Karena itu, kita harus berhenti menyalahkan, dan mulai mendukung. Penyandang TBC seharusnya diperlakukan sebagai pejuang, bukan pesakitan. Mereka yang dengan tekun menjalani pengobatan selama 6 hingga 12 bulan, di tengah efek samping obat dan tekanan sosial, adalah pribadi-pribadi tangguh yang layak diapresiasi. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tapi juga melindungi masyarakat dari penularan yang lebih luas.
Kita tidak akan bisa mengakhiri TBC di tahun 2030, seperti yang menjadi target global, jika stigma masih menjadi tembok yang memisahkan pasien dengan layanan kesehatan. Maka, tugas kita bersama adalah meruntuhkan tembok itu, dengan edukasi, empati, dan keberpihakan terhadap kemanusiaan. Kampanye anti-stigma harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengendalian TBC. Media massa, tokoh agama, tenaga kesehatan, keluarga, dan para penyintas harus menjadi garda depan dalam menyuarakan bahwa: “TBC bisa sembuh. Yang menyakitkan bukan penyakitnya, tapi sikap kita terhadapnya.”
Mari ubah paradigma kita dalam memandang penderita TBC. Mari kita lawan TBC dengan ilmu pengetahuan dan empati, bukan dengan celaan dan prasangka. Sudah saatnya kita merangkul mereka yang terinfeksi, bukan malah mengucilkan atau menjauhi. Di hadapan penyakit, yang dibutuhkan bukanlah penghakiman, melainkan rasa kemanusiaan dan solidaritas. Penyembuhan fisik memang penting, tetapi penyembuhan luka batin akibat stigma tak kalah urgennya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para penderita. Hanya dengan menghapus stigma dan diskriminasi, kita dapat mendorong lebih banyak orang untuk berani memeriksakan diri dan menjalani pengobatan. Sebab, hanya dengan mengakhiri stigma, kita benar-benar memulai langkah besar untuk mengakhiri TBC di Indonesia. (ndy)