0leh : Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Sumatera Post, penyuka seni tradisi tinggal di Semarang
Semarang Malam itu, aula GSG Sudarto, Kampus Undip Tembalang, berubah menjadi ruang waktu yang menembus dua abad. Pertunjukan dibuka dengan pembacaan puisi “Diponegoro” karya Chairil Anwar yang dilantunkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Undip Prof. Alamsyah M. Hum dengan ciamik.
Lampu-lampu temaram memantulkan bayang-bayang prajurit, doa para santri, dan langkah seorang bangsawan yang memilih berjuang di jalan kebenaran. Dalam denting gamelan githung Swara dan tembang Jawa yang lirih, kisah “Banjaran Diponegoro” kembali hidup—sebuah pagelaran ketoprak hasil kolaborasi antara Universitas Diponegoro dan Ngesti Pandowo, disutradarai oleh Sunarno, yang menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis ke-68 Undip.
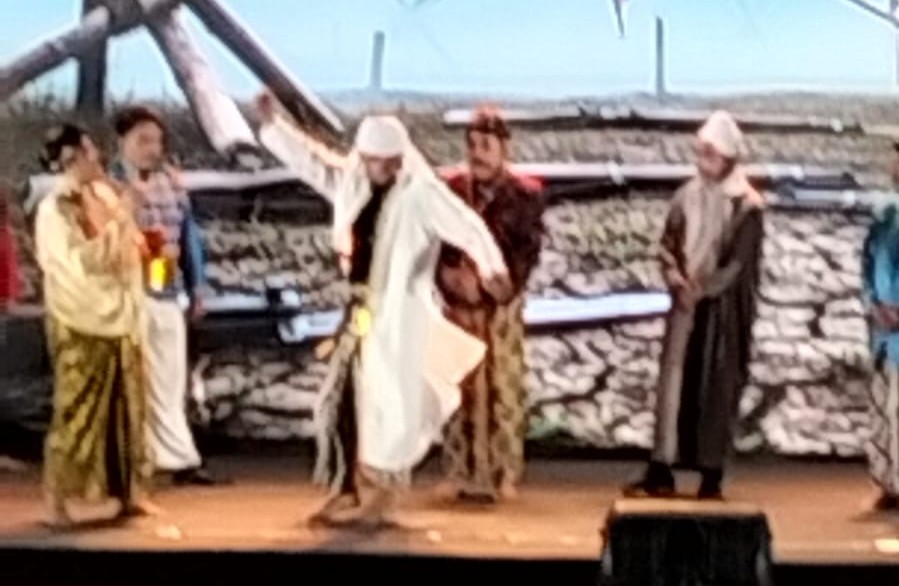 Sandiwara Sejarah yang Menyentuh Jiwa
Sandiwara Sejarah yang Menyentuh Jiwa
“Banjaran Diponegoro” bukan sekadar lakon perang atau perebutan kuasa. Ia adalah narasi batin tentang perjuangan, spiritualitas, dan cinta tanah air. Di tangan para dosen dan seniman yang menyatu di panggung, sosok Pangeran Diponegoro—yang diperankan oleh Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.S.—hadir bukan hanya sebagai pahlawan nasional, tetapi sebagai manusia dengan segala gelora, luka, dan keteguhan iman.
Kisah bergulir dengan halus dari Tegalrejo yang damai menuju medan perang yang membara. Adegan-adegan bersama Kyai Mojo (Prof. Dr. Ir. Agus Indarjo) dan Sentot Prawirodirjo (Prof. Dr. ret. nat. Heru Susanto) membangun irama perjuangan yang penuh nilai spiritual dan kesetiaan. Bahkan sosok antagonis seperti Jenderal De Kock (Prof. Dr. Mohammad Djaeni, S.T., M.) dihadirkan dengan keanggunan artistik yang menggambarkan benturan dua dunia: kolonialisme dan kebangsaan.
Ketoprak sebagai Cermin Nilai dan Identitas
Pagelaran ini mengingatkan bahwa seni tradisi bukan sekadar hiburan, melainkan ruang perenungan kolektif. Dalam gemerincing saron dan kendang, penonton diajak merenungi kembali arti kepemimpinan sejati—tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan tentang pengabdian tanpa pamrih kepada rakyat.
Rektor Undip menegaskan, pemilihan kisah Pangeran Diponegoro sebagai tema Dies Natalis bukanlah kebetulan. “Ini adalah ajakan bagi generasi muda untuk memahami perjuangan bukan sebagai masa lalu, tetapi sebagai napas yang menghidupi bangsa,” ujarnya.
Ketika Akademisi Menjadi Seniman
Yang membuat pagelaran ini istimewa adalah keberanian para profesor, dosen, dan akademisi untuk menanggalkan jubah ilmuwan dan mengenakan busana kebesaran budaya. Mereka tidak sekadar berakting, tetapi menjiwai peran dengan kesungguhan seorang pelajar yang mencintai warisan leluhur. Kolaborasi antara Undip dan Ngesti Pandowo membuktikan bahwa dunia akademik dan kesenian dapat berjalan seiring dalam menjaga nilai-nilai luhur kebangsaan.
Warisan yang Dihidupkan Kembali
Ketika tirai panggung menutup, tepuk tangan panjang menggema, bukan hanya untuk para pemain, tetapi untuk semangat yang mereka hidupkan kembali—semangat Pangeran Diponegoro yang menolak tunduk pada ketidakadilan. “Banjaran Diponegoro” bukan hanya pagelaran, melainkan doa budaya agar bangsa ini tak pernah lupa pada asal keberaniannya.
Para Pendukung Pementasan Ketoprak “Banjaran Diponegoro”
Di balik gemuruh tepuk tangan yang menggetarkan aula GSG Sudarto Universitas Diponegoro, berdiri barisan pengabdi seni yang menyalakan kembali nyala sejarah lewat panggung ketoprak klasik Banjaran Diponegoro. Mereka datang dari berbagai disiplin ilmu dan generasi—para profesor, akademisi, mahasiswa, dan seniman—namun di bawah cahaya panggung, mereka bersatu dalam satu peran: penjaga jiwa budaya bangsa.
Di kursi sutradara, Sunarno dari Ngesti Pandowo menautkan naskah dan napas cerita dengan tangan seorang maestro. Ia bukan hanya mengarahkan gerak dan dialog, tetapi menanamkan ruh ketoprak yang sarat nilai kepemimpinan dan spiritualitas Jawa. Di sisinya, Laura Andri R.M., S.S., M.A., sang Pimpinan Produksi, menjadi denyut organisasi—menyatukan disiplin akademik dan kebebasan seni agar harmoni tetap terjaga di balik panggung.
Sebagai Pangeran Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. tampil memukau: tenang, berwibawa, dan penuh perenungan. Ia menjadi pusat gravitasi yang menuntun kisah dari Tegalrejo yang damai menuju kobaran Perang Jawa. Di sisinya, Prof. Ir. Edy Rianto, M.Sc., Ph.D., I.P.U. sebagai Buminoto menghadirkan sosok rakyat yang setia dan berani, sedangkan Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. tampil berwibawa sebagai Pangeran Adinegoro—antagonisme yang lembut antara diplomasi dan idealisme.
Keanggunan terpancar dari Prof. Dr. Endang Larasati, M.S. sebagai Gusti KRA Ageng, bangsawan yang arif dan penuh kebijaksanaan. Prof. Dr. Ir. Agus Indarjo memerankan Kyai Mojo dengan keteduhan rohani yang mengalir, berpadu dengan Prof. Dr. ret. nat. Heru Susanto, S.T., M.T. sebagai Sentot Prawirodirjo yang muda dan berapi-api. Sementara Prof. Dr. Mohammad Djaeni, S.T., M.Eng. memerankan Jenderal De Kock dengan ketegasan khas kolonial—sosok lawan yang justru menegaskan makna perjuangan.
Deretan tokoh pendukung memperkaya semesta lakon: Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, M.T. sebagai Purboyomangkubumi; Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D. sebagai Raden Mas Mustahar (Ontowiryo); Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA sebagai Raden Mas Surojo; dan Prof. Dr. Ir. Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyo, M.M., M.Sc., Ph.D. sebagai Residen Hendrik Smissaert, simbol kelicikan kekuasaan kolonial.
Kehadiran para perempuan bangsawan memberi rona lembut sekaligus kokoh pada pementasan ini: Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. sebagai Gusti Kanjeng Ratu Hemas; Prof. Dr. Yetty Rochwulaningsih, M.Si. sebagai GKR Tegalrejo (Sepuh); Prof. Dian Ratna Sawitri, S.Psi., Ph.D. sebagai Raden Ajeng Mangkarowati; Prof. Dr. Endang Susilowati, M.A. sebagai GKR Wandhan; serta Prof. Dr. Dra. Endah Sri Hartatik, M.Hum. sebagai Kanjeng Ratu Kencana.
Sementara Tim Ngesti Pandowo menyalakan denyut tradisi melalui para santri dan rakyat kecil—mereka yang menjadi penopang sejarah sekaligus sumber energi batin bangsa. Dari balik naskah dan gamelan, juga hadir sosok-sosok yang menjaga ritme pementasan: Budi Lee (Asisten Sutradara), dan Puguh, M.Hum. yang menghidupkan dimensi dramatik lewat sentuhan teaterikal yang halus.
Para penafsir karakter rakyat—Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D. (Ki Bogel), Prof. Dr. Alamsyah, M.Hum. (Ngabei Tepasana), serta Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol. Admin. (Ngabei Panambang)—menghadirkan humor dan kebijaksanaan di tengah heroisme, menghadirkan keseimbangan yang khas ketoprak klasik.
Pementasan juga diperkuat oleh jajaran tokoh tambahan: Ngabei Dirgayuda, Tumenggung Yudanegara, Patih Danurejo VI, hingga para prajurit dan rakyat seperti Cici Ranita, Eka Fadila, dan Bagas Ghanesa. Mereka, bersama Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp. Onk., Prof. Sugiharto, S.Pt., M.Sc., dan Prof. Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., menjahit realisme dan semangat gotong royong di atas panggung.
Menambah semarak, sesi dagelan dihidupkan oleh Bagio “Gareng” Ngseti, Ali “Bajaj Bajuri”, dan Nining Tirang, yang menghadirkan tawa tanpa menghapus kesakralan kisah.
Di bawah denting saron dan kendang, mereka semua menyatu menjadi satu kesatuan jiwa: dari bangsawan hingga rakyat, dari dosen hingga mahasiswa, dari akademisi hingga seniman panggung. Ketoprak “Banjaran Diponegoro” pun bukan lagi sekadar lakon sejarah—melainkan perayaan jati diri bangsa, doa budaya agar semangat perjuangan tak lekang oleh waktu.keberanian, pengabdian, dan cinta tanah air adalah warisan yang harus terus dijaga. (*)




