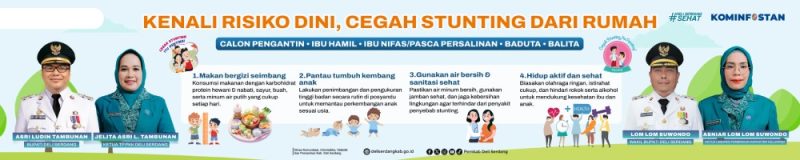Semarang — Di jantung kawasan Pecinan, pada sebuah gedung berusia ratusan tahun bernama Boen Hian Tong, cahaya dupa naik perlahan, berpilin bersama bunyi gamelan dan denting doa. Minggu pagi, 21 September 2025, ratusan umat dan pegiat lintas agama berhimpun. Mereka datang bukan sekadar untuk menjalankan tradisi, tetapi untuk menyalakan kembali api bakti: King Ho Ping, sembahyang penghormatan kepada arwah leluhur dan jiwa-jiwa tanpa nama, yang sejak berabad lalu dilaksanakan setiap bulan tujuh penanggalan Imlek.
Acara dimulai dengan suasana khidmat. MC Venty mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu, lalu mengajak hadirin meredam suara, menundukkan gadget, dan masuk ke dalam hening. Di pintu masuk, barisan umat memberi hormat kepada Thien, Sang Sumber Kehidupan. Dari sana langkah diarahkan menuju altar leluhur, di mana nama-nama yang dititipkan oleh keluarga terpajang di meja panjang, menunggu untuk disapa doa. Pemimpin doa, Wenshi Andi Gunawan, memimpin penghormatan, menyerahkan sembah kepada arwah yang lebih dulu mendahului, sekaligus menyatukan batin semua yang hadir.
 Doa Lintas Iman, Harmoni dalam Suara
Doa Lintas Iman, Harmoni dalam Suara
Yang membuat King Ho Ping di Semarang begitu khas adalah wajahnya yang inklusif. Dari satu altar, doa mengalir dalam delapan bahasa iman: Ki Renggo dari Penghayat Kepercayaan, Romo Wito Karyono dari Katolik, Pendeta Stevanus Wawan Setiawan dari Kristen Protestan, Oei Tau Ping dari Tao, Pendeta Agga Dhammo Warto dari Buddha, Pak Mangku Muhadi dari Hindu, KH. Muhammad Abdul Qadir (Gus Qadir) dari Islam, hingga Wenshi Andi Gunawan dari Khonghucu.
Satu demi satu mereka naik ke panggung, mengalunkan doa tiga menit, masing-masing dengan warna tradisinya sendiri. Tetapi meski kata-kata berbeda, inti pesannya satu: keselamatan bagi arwah, kedamaian bagi semesta, dan kasih di antara sesama.
Refleksi yang menyusul kian menegaskan ikatan lintas iman ini. Ki Renggo mengingatkan bahwa menghormati leluhur adalah menghormati akar kemanusiaan. Pendeta Stevanus berbicara tentang kasih yang melampaui batas keyakinan. Sementara Gus Qadir dengan suara teduh menekankan pentingnya merawat keadilan sebagai buah iman.
Sembahyang Rebutan: Dari Leluhur untuk Semua Selepas doa dan refleksi, tiba saatnya umat maju membawa nama leluhur yang dititipkan di altar. Wajah-wajah tampak teduh, mata sebagian berkaca-kaca, bibir berbisik doa-doa pribadi yang mungkin hanya bisa dipahami oleh hati.
Di sudut lain, panitia mempersiapkan simbol paling khas King Ho Ping: perahu kertas raksasa berisi sesajen, perlambang kendaraan arwah kembali ke alamnya. Kelak perahu ini akan dibakar, api menjelma jalan pulang bagi roh-roh yang telah dititipkan doa.
Namun ada pula sisi sosial yang tak kalah penting. Dari donasi sukarela, terkumpul sembako yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Tradisi “sembahyang rebutan”—di mana makanan altar diperebutkan atau dibagikan—di sini menemukan makna baru: bukan sekadar rebutan berkah, tetapi berbagi kasih dari leluhur untuk generasi yang masih hidup.
“King Ho Ping bukan sekadar ritual leluhur, tetapi juga momen kebersamaan lintas keyakinan. Kita belajar memberi, mendoakan, dan saling menyentuh hati dalam sunyi,” ujar Agung Kurniawan, ketua panitia, dengan mata berbinar.
Harmoni yang Menyeberangi Zaman
Puncak acara ditutup dengan doa Jing He Ping (敬和平) 2576 Kongzili yang dipanjatkan Wenshi Andi Gunawan. Kata-kata doa itu mengalun bak kidung: memohon kepada Tiān agar umat manusia dijauhkan dari keserakahan, agar kebajikan tegak, agar leluhur diterima dalam ketenteraman.
Di akhir, dua bilah kayu Pak Poe dilempar. Simbol kuno itu menentukan: apakah roh-roh sudah berkenan, apakah acara boleh diakhiri. Kayu terbuka, tanda restu turun. Senyum merekah, lega menyelimuti wajah panitia dan umat.
Siang hari, ketika nasi putih dan sayur tersaji dalam jamuan sederhana, hadirin duduk bersama. Tidak ada sekat agama, tidak ada perbedaan keyakinan. Yang ada hanyalah manusia yang sama-sama menghormati mereka yang telah berpulang, sambil merajut kasih untuk sesama yang masih bernafas.
Pelita di Tengah Zaman Bising
King Ho Ping di Boen Hian Tong bukan sekadar ritus. Ia adalah pengingat bahwa doa bisa menjembatani masa lalu dan masa depan, bahwa kasih bisa menyeberangi batas iman, dan bahwa keharmonisan hanya bisa lahir bila manusia mau saling menundukkan hati.
Di tengah dunia yang gaduh oleh perbedaan, ritual ini hadir sebagai pelita: sederhana, hening, namun memberi cahaya. Ia mengajarkan bahwa pada akhirnya, kita semua adalah anak-anak dari leluhur yang sama, pewaris cinta kasih yang tak lekang oleh waktu. (Christian Saputro)