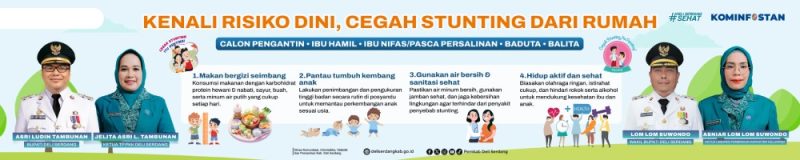Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Sumatera Post, tinggal di Semarang.
Sore itu, Rabu (29/10/2025), langit Semarang tampak teduh. Di halaman Universitas PGRI Semarang, angin berembus pelan membawa aroma bunga kenanga dari taman kampus. Di dalam Balairung, suara gamelan mulai bergetar—lirih, namun mampu menggugah nurani siapa pun yang datang. Nada-nada itu seperti menyapa: “Selamat datang di Mahakarya.”
Di bawah tema “Lestari di Panggung Tradisi”, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sangkatama kembali menorehkan jejak budaya lewat Mahakarya #7—sebuah persembahan seni yang tak hanya menampilkan karawitan, tari, dan wayang, tetapi juga menyalakan kembali bara kebudayaan di dada generasi muda.
Pagi yang Sibuk, Sore yang Sakral
Sejak matahari belum tinggi, halaman kampus sudah riuh oleh kesibukan.
Mahasiswa memanggul gamelan, menata panggung, menyetrika kostum, menyiapkan sesaji. Di wajah mereka tersirat semangat yang tak kalah hangat dari kopi yang mengepul di sudut backstage.
Pukul 15.30, pintu Balairung dibuka. Penonton berdatangan—dosen, mahasiswa, seniman, hingga masyarakat umum. Gamelan yang mengalun lembut menyambut mereka seperti tamu agung. Saat acara resmi dibuka pukul 16.00 WIB, semua berdiri tegap menyanyikan Indonesia Raya dan Mars UPGRIS. Ada getar halus di dada: rasa cinta tanah air yang menemukan bentuknya dalam budaya.
Ketua panitia, Anin, tampil dengan suara lantang namun teduh. Ia menceritakan perjalanan panjang persiapan Mahakarya yang telah dikerjakan berbulan-bulan. “Mahakarya ini bukan pertunjukan biasa,” ujarnya, “ini cara kami berdialog dengan leluhur.” Pagelarn dibuka dengan resmi dengan penanda pemukuan gong oleh Prasena Arisyanto, S.Pd, M.Pd dari UPGRIS.
Tari, Gamelan, dan Gerak yang Bertutur
Satu per satu, panggung hidup oleh keindahan yang menari. Tari Golek Manis dari Egam membuka suasana dengan kelembutan gerak yang seolah mengajarkan kesabaran perempuan Jawa. Disusul Golek Ayun-Ayun (SCU), Geol Denok (Sangkatama), Mojang Priyangan (Unimus), dan Sri Ganyong (Egam).
Setiap hentakan kaki, setiap putaran tangan, bukan sekadar koreografi. Ia adalah bahasa tubuh yang menuturkan sejarah—tentang kasih, kesetiaan, dan kegigihan yang diwariskan berabad-abad.
Menjelang senja, saat matahari perlahan menurunkan cahayanya, gamelan berhenti sejenak. Waktu ISHOMA menjadi jeda kecil sebelum malam menyalakan pesonanya.
Dalang Kecil, Pesan yang Besar
Malam pun turun dengan tenang. Di atas panggung, dua bocah dalang—Danen dan Dafan—menduduki blencong dengan percaya diri. Suara mereka jernih, jenaka, dan penuh makna. Wayang yang mereka mainkan bukan hanya kisah perang dan kepahlawanan, tapi juga nasihat kehidupan yang sederhana: tentang jujur, tentang sabar, tentang mencintai tanah air.
“Wayang itu bukan masa lalu,” kata salah satu penonton, sambil mengusap matanya yang basah, “tapi cermin kita hari ini.”
Harmoni Seratus Tahun: Menghidupkan Semangat Ki Narto Sabdo
Tak berhenti di panggung UPGRIS, Mahakarya #7 juga menjadi bagian dari peringatan “Harmoni Seratus Tahun”—memperingati seabad kelahiran maestro karawitan dan pedalangan, Ki Narto Sabdo.
Dua hari sebelumnya, di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, dilakukan prosesi jamasan patung Ki Narto Sabdo. Dalang sepuh Ki Suradji memimpin ritual dengan penuh khidmat. Air yang disiramkan ke patung perunggu bukan hanya menyucikan logam, tapi juga menyucikan ingatan. “Ini bukan sekadar menyiram patung,” ujarnya, “tapi menyiram kembali nilai-nilai yang diwariskannya.”
Mahasiswa Sangkatama hadir dengan pakaian adat dan sesaji simbolik, menunjukkan bahwa estafet budaya tidak pernah putus. Dari tangan para maestro, warisan itu kini berpindah ke generasi muda.
Wayangan Kolaboratif: Tripama Kawedhar
Puncak acara malam itu adalah wayangan kolaboratif bertajuk “Tripama Kawedhar”—lakon yang mengajarkan tiga teladan luhur kepemimpinan. Empat dalang lintas generasi: Ki Jagad Bilowo, Ki Mohammad Asy’Aril, Dr. Bambang Sulanjari, serta duo muda Danendra dan Dafandra Djuanda, tampil estafet menghidupkan kisah dengan harmoni yang menggetarkan.
Tabuhan gamelan, suluk lirih, dan bayangan wayang di layar putih berpadu menjadi simfoni spiritual. Penonton terdiam, seolah tersihir oleh kedalaman makna yang melintas dari masa lalu ke masa kini.
Menjaga Api yang Tak Pernah Padam
Ketika gong pamungkas ditabuh, tirai turun perlahan. Tepuk tangan panjang menggema di Balairung. Malam itu, bukan hanya sebuah pertunjukan yang usai, tetapi juga janji yang diteguhkan: bahwa budaya tidak akan dibiarkan padam.
Sangkatama membuktikan, pelestarian budaya tidak selalu harus megah. Ia bisa sederhana, asal tulus. Ia bisa sunyi, asal berakar.
Dan malam itu, di Universitas PGRI Semarang, akar itu tumbuh kembali—menyapa masa depan dengan nada gamelan, gerak tari, dan bayangan wayang yang berkata lembut: “Selama masih ada yang mencintai, budaya takkan pernah mati.” (*)