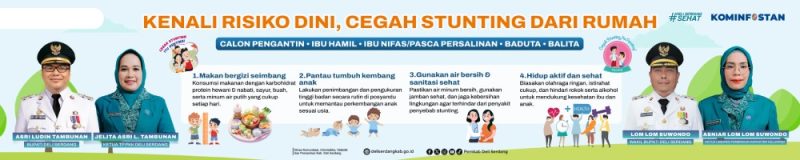Oleh : Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Sumatera Post, tinggal di Semarang.
Malam menurunkan cahaya lembutnya seusai diguyur hujan di langit Semarang. Di halaman Bandara Ahmad Yani Lama, tempat yang biasanya dipenuhi deru baling-baling dan langkah-langkah militer, malam itu udara bergetar oleh denting gamelan dan aroma dupa yang perlahan membumbung.
Di panggung terbuka, sebuah dunia lama kembali hidup — dunia yang dihidupi oleh tokoh-tokoh wayang orang Ngesti Pandowo dalam lakon “Petruk Kilangan Pethel, Werkudara Kilangan Gada”.
Pagelaran ini menjadi persembahan istimewa dalam rangka Mangayubagya HUT Penerbad ke-66. Namun, di balik gemerlap perayaan, terselip semangat yang jauh lebih dalam: semangat untuk menautkan langit modernitas dengan bumi tradisi, menghadirkan napas budaya di tengah dentuman teknologi dan disiplin militer.
Sinergi Antara Langit dan Laku Budaya
“Acara ini bukan sekadar hiburan,” ujar Saroso, Kabid Kebudayaan Disbudpar Kota Semarang, “tetapi ruang untuk melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi.”
 Kata-katanya tak sekadar formalitas. Di tengah gemuruh pembangunan dan percepatan zaman, Disbudpar dan Penerbad bersinergi menciptakan panggung yang membuktikan: seni klasik tidak pernah kehilangan makna.
Kata-katanya tak sekadar formalitas. Di tengah gemuruh pembangunan dan percepatan zaman, Disbudpar dan Penerbad bersinergi menciptakan panggung yang membuktikan: seni klasik tidak pernah kehilangan makna.
Maka berdirilah panggung kayu di bawah bintang-bintang, di mana humor Petruk dan keperkasaan Werkudara bersanding dengan disiplin prajurit udara. Kolaborasi ini seperti menyatukan dua dunia — dunia yang menatap masa depan, dan dunia yang menggali hikmah masa lampau.
Petruk: Cermin Rakyat yang Jenaka dan Bijak
Lakon Petruk Kilangan Pethel menjadi pintu bagi penonton untuk menertawakan, sekaligus memahami hidup. Petruk — si punakawan dengan wajah lucu dan tutur yang tajam — kehilangan pethel, pusaka yang menjadi simbol kecerdikan dan martabatnya. Ia mencari, jatuh, tertipu, lalu bangkit lagi. Dalam kegagalannya, Petruk menemukan kembali dirinya.
Sutradara Budi Lee menampilkan kisah ini dengan sentuhan yang segar. Gerak tari penuh dinamika, aransemen gamelan karya Githung Swara yang lembut namun bergelora, serta koreografi Paminto Krisna yang enerjik menjadikan panggung itu hidup — bukan sekadar tontonan, tapi perjalanan rasa.
Petruk, dengan segala kejenakaannya, bukan sekadar badut dalam dunia wayang. Ia adalah suara rakyat: cerdas, lugu, kadang sinis, tetapi jujur dan apa adanya. Dalam kehilangan pethel-nya, tersirat makna bahwa setiap manusia pun kadang kehilangan sesuatu yang membuatnya berharga, dan justru di sanalah kita menemukan makna sejati keberanian.
Werkudara: Ksatria yang Diuji oleh Kehilangan
Berbeda dengan Petruk, kisah Werkudara Kilangan Gada menampilkan wajah kehidupan yang lain — gagah, tegas, namun rapuh dalam sunyi. Gada Rujakpolo bukan sekadar senjata pamungkas, melainkan lambang tanggung jawab, kuasa, dan kehormatan. Saat gada itu hilang, Werkudara dipaksa menatap dirinya sendiri tanpa atribut kekuatan.
Adegan Werkudara kehilangan Gada selalu menjadi momen yang mengguncang batin. Dalang Ngesti Pandowo dengan sulukan lirih membangun suasana batin yang pekat: bahwa kekuatan sejati tak lahir dari benda, melainkan dari jiwa yang tetap teguh dalam kehilangan.
Kisah ini seolah menyapa setiap manusia di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Di balik kekuasaan, jabatan, dan prestasi, terselip pertanyaan yang sama: siapa kita ketika semua itu hilang?
Ketika Wayang Menyapa Langit
Pagelaran malam itu menegaskan bahwa wayang orang bukan sekadar peninggalan masa lalu. Ia adalah cermin yang masih bisa memantulkan wajah hari ini. Di tengah riuh bandara dan lampu kota, Ngesti Pandowo membangun jagat semesta di atas panggung, menghadirkan Petruk dan Werkudara sebagai dua sisi kehidupan — tawa dan perjuangan, kehilangan dan keteguhan.
Para penonton, dari pejabat hingga warga, larut dalam irama gamelan yang mengalun seperti detak jantung Nusantara. Ketika sulukan terakhir menggema dan tirai panggung perlahan turun, suasana hening sejenak. Tak ada tepuk tangan berlebihan — hanya rasa haru, kagum, dan kesadaran bahwa tradisi ini masih hidup, berdetak lembut di tengah kemajuan zaman.
Wayang orang malam itu bukan sekadar persembahan untuk Penerbad, tetapi juga persembahan bagi semesta kebudayaan. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati — baik di langit maupun di bumi — selalu bersumber dari kebijaksanaan, kesetiaan, dan cinta pada akar budaya sendiri. (*)