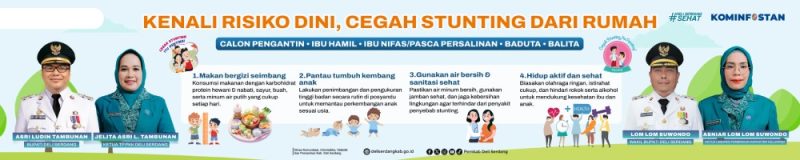Oleh: Yandi Syaputra Hasibuan
Siapa yang tidak mengenal pasar malam. Sebuah arena mirip pasar tradisional namun dilengkapi berbagai sarana hiburan. Di daerah perkampungan, pasar malam kerap menjadi sasaran pelarian masyarakat untuk menghilangkan kepenatan setelah seharian bekerja.
Ada banyak sarana hiburan ditawarkan di pasar malam. Sebut saja lempar gelang, bianglala atau tempat berayun yang dapat membuat perut pengunjung mual hingga muntah, permainan ketangkasan sarat judi, pertunjukan kesenjan, dan fasilitas lainnya.
Selain sarana hiburan, berbagai tipe dan karakter manusia dari semua kelompok umur dengan mudah dapat ditemui di pasar malam. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sampai dengan mereka yang “styles” hingga “bodo amat” dengan penampilannya karena sekadar datang untuk melihat-lihat.
Di Indonesia, pasar malam menjadi salah satu daya tarik wisata yang sudah “mendarahdaging”, terlebih bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Biaya yang tidak terlalu mahal menjadi salah satu alasannya.
Berbeda halnya jika berkunjung ke mall, mengingat tempat ini lebih didominasi oleh kaum berduit. Jikapun ada orang kurang mampu bermain di mall, hal ini lebih kepada pemaksaan terhadap status ekonominya semata.
Bagi generasi milenial pasar malam menjadi sasaran empuk untuk melepas kepenatan semalam suntuk di tengah riuhnya tumpukan pekerjaan pada siang hari. Sebaliknya bagi muda-mudi yang belum bekerja, baik mahasiswa ataupun pelajar, pasar malam menjadi tempat yang cocok untuk dikunjungi bersama teman atau pasangan.
Pasar malam bagi masyarakat kelas bawah sudah menjadi arena yang menguntungkan secara ekonomi. Mereka memanfaatkan pasar malam untuk ajang mengumpulkan rupiah dengan cara menjual makanan dan minuman, pernak-pernik, hingga jasa parkir kendaraan.
Begitu strategisnya peran dan kehadiran pasar malam, tentu saja membuat tempat sepert ini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Bukan hanya menjadi pusat transaksi ekonomi dan sarana hiburan rakyat, pasar malam saat ini telah menjelma menjadi alternatif destinasi wisata yang ekonomis.
Lantas, bagaimana sejarah lahirnya pasar malam? Dalam catatan sejarah, pasar malam sudah mulai ada sejak abad ke-6 dan 7 Masehi di masa Dinasti Sui di Tiongkok (Frederick Wells W., A History of China).
Dikatakan pasar malam karena proses transaksi dagang dilaksanakan pada malam hari, layaknya pasar tradisional yang beroperasi di siang hari. Segala hal yang diperjualbelikan sama seperti pasar tradisional. Hanya saja waktunya berbeda, yakni malam hari.
Di Indonesia, keberadaan pasar malam sudah ada di masa kolonial Belanda, dimulai sejak tahun 1870 atau setelah terbitnya Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) dan Undang-Undang Gula (Saka Wet) oleh Pemerintah Hindia-Belanda (R.M. Leirissa, dkk., Sejarah Perekonomian Indonesia)
Regulasi ini menyebabkan liberalisasi ekonomi yang begitu luas. Salah satu bukti paling nyata ialah pesatnya pertumbuhan industri perkebunan. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Timur. Sumatera Timur bahkan menjelma menjadi sentra industri perkebunan modern sejak akhir abad ke-19.
Perusahaan perkebunan (onderneming) yang ada di Sumatera Timur saat itu bukan hanya dimiliki oleh pengusaha Belanda saja, melainkan pengusaha asing lainnya seperti Jerman, Amerika Serikat, Swiss, Polandia, dan sebagainya (Jan Breman, Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Awal Abad ke-20).
Berdasarkan catatan Karl J. Pelzer dalam bukunya berjudul “Tuan Kebun dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria” (1985), pertumbuhan industri perkebunan juga meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Para tenaga kerja ini sengaja direkrut dan dipekerjakan di perkebunan. Mereka ini yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “kuli”.
Para kuli biasanya didatangkan dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Hindia-Belanda, tetapi juga dari luar negeri. Khusus di Sumatera Timur, para kuli perkebunan banyak didatangkan dari Pulau Jawa, Tiongkok, dan India.
Sebelum bekerja di perkebunan, para kuli terlebih dahulu diikat dengan perjanjian kerja (kontrak). Dari sinilah muncul istilah “kuli kontrak”. Kontrak ini biasanya disetujui selama satu tahun dan gaji diberi terlebih dahulu. Tujuannya supaya para kuli giat bekerja (Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Konfrontasi: Di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979).
Akan tetapi pengalaman bekerja para kuli di perkebunan tidaklah seperti yang dibayangkan. Pasalnya, ada kuli yang bekerja hingga mati akibat beban kerja yang berat atau karena dihukum akibat melakukan pelanggaran.
Tidak jarang para kuli harus tinggal dalam satu barak yang diisi hingga puluhan orang. Jika seorang kuli buang air sembarangan, maka dia akan dikeluarkan dari barak tersebut.
Dengan kondisi kehidupan seperti itu, banyak di antara para kuli pada akhirnya menderita sakit dan bahkan sampai meninggal dunia. Tidak heran mereka lebih memilih melarikan diri karena tidak tahan dengan beratnya beban kerja dan aturan perusahaan perkebunan yang dianggap tidak manusiawi.
Meskipun aturan kerja relatif ketat, namun perusahaan perkebunan tetap menyadari kehadiran tenaga kerja juga penting. Demi menjamin para kuli tetap merasa nyaman dan betah bekerja di perkebunan, maka perusahaan membuat berbagai kebijakan strategis. Salah satunya ialah pasar malam.
Pasar malam sendiri dibuat sebagai sarana hiburan bagi para kuli perkebunan. Biasanya pasar malam digelar setelah para kuli menerima gaji. Di tempat ini, pengelola pasar malam biasanya menawarkan berbagai sarana hiburan, perjudian, minuman keras, seni pertunjukan wayang, termasuk menjual pakaian dan barang berharga.
Ironisnya, kehadiran pasar malam telah secara langsung menyedot penghasilan para kuli. Sebagian besar kuli justru menghabiskan gaji mereka di pasar malam, baik untuk membeli berbagai barang kebutuhan mereka, pakaian, perhiasan, makanan dan minuman, ataupun untuk berfoya-foya.
Pada akhirnya, para kuli yang kehabisan uang terpaksa berhutang dengan sistem persekot kepada perusahaan perkebunan, dengan syarat kontrak kerja mereka ditambah. Kondisi ini tentu saja memaksa para kuli tetap bekerja di perkebunan hingga akhir hayat mereka karena tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya (Mohammad Said, Koeli Koentrak Tempo Doeloe dengan Derita dan Kemarahannya).
Buya Hamka dalam novel fenomenalnya berjudul “Merantau ke Deli” (1939), mengisahkan kehidupan para kuli perkebunan di Deli, Sumatera Timur. Setelah menerima gaji yang tidak penuh akibat dipotong hutang, para kuli pun mengalihkan perhatiannya untuk mengunjungi pasar malam.
Bukan hanya datang untuk membeli berbagai barang kebutuhan hidupnya, para kuli juga melampiaskan kepenatan yang meraka alami setelah bekerja dengan membeli beraneka macam jajanan, bermain judi, atau sekadar jalan-jalan dan cuci mata. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk kerinduan dan pelampiasan menikmati kesenangan dunia setelah satu bulan bekerja, meskipun harus menerima konsekuensi kehilangan seluruh gajinya.
Hal yang juga menarik dari novel Buya Hamka ialah kehadiran para pedagang Minangkabau, karena menjadikan pasar malam sebagai ladang keberkahan. Sebab mereka dapat menjual kain dan barang dagangannya, yang kadangkala cukup susah diboyong oleh pembeli.
Dari uraian ini sangat disadari bahwa kehadiran pasar malam dalam perkembangan industri perkebunan di Indonesia pada masa kolonial Belanda telah menjadi senjata ampuh bagi para pengusaha perkebunan untuk membuat para kuli menjadi “lupa daratan”.
Pasar malam dengan segala sarana dan kelengkapannya memang menjadi senjata ampuh perusahaan perkebunan untuk memikat para kuli yang haus akan hiburan. Keadaan ini pula yang membuat para kuli tidak sayang menghabiskan seluruh penghasilan mereka, meski pada akhirnya harus terjerat hutang.
Hanya saja tidak semua kuli perkebunan berpikiran seperti itu. Sebab ada juga dari mereka justru memanfaatkan sebagian gajinya untuk ditabung demi menutupi keperluan yang lebih besar di kemudian hari. Sikap cermat seperti inilah yang umum dilakukan oleh para kuli Tionghoa saat itu.
Walaupun pasar malam adalah bagian dari produk kolonial, bukan berarti kita harus bersikap antipati. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa pasar malam saat ini menjelma sebagai sebuah kekuatan ekonomi, terutama bagi rakyat kecil. Tidak heran pasar malam tetap eksis dan selalu mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia.
Bagi kaum milenial, kehadiran pasar malam tidak hanya dimaknai sebagai fenomena sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, tetapi juga harus dipahami sebagai bagian dari dampak proses industrialisasi di masa lalu.
Penulis adalah Mahasiswa Strata 2 Ilmu Sejarah, FIB, USU