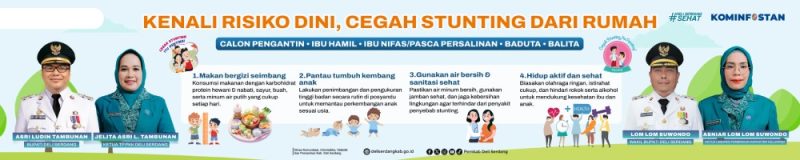Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro *)
Langit Semarang sore itu memekat. Awan hitam bergantung seperti firasat yang enggan pergi. Ketika senja beringsut menuju malam, rinai gerimis pun turun perlahan, lalu menderas, seolah hendak membatalkan harapan. Namun wajah-wajah yang berkumpul di halaman Klenteng See Ong Kiong pada Sabtu (28/6) itu tetap menengadah, bukan pada langit, melainkan pada harapan yang telah lama disulam: Pertunjukan “Pendekar Rompi Macan” akan tetap digelar.
Dalam naungan Festival Bubak Semarang 2025, panggung sudah disiapkan. Meski langit memuntahkan air dan malam menggigil, semangat tetap disulam dari keberanian: bahwa seni adalah doa yang tak bisa ditunda, pertunjukan adalah janji yang tak boleh dibatalkan.
Sebelum kisah sang pendekar dibabar dalam narasi panggung, dua tarian membuka gerbang: Tari Gongfu dari Sanggar Nyi Pandan Sari dan Tari Mangzhong dari Tandawa Ratri. Keduanya bukan sekadar prolog visual, melainkan pemantik jiwa.
 Tari Gongfu menghantarkan energi lewat kekuatan gerak yang terjaga, presisi yang menggetarkan. Berakar dari bela diri Tionghoa, namun di tangan para penari Semarang, tari ini menjelma menjadi puisi tubuh: menyatu antara kekuatan dan kelembutan, antara kedisiplinan dan kebijaksanaan. Ia adalah tubuh yang berbicara lintas etnis, mengguratkan pesan multikulturalisme di panggung yang basah oleh gerimis.
Tari Gongfu menghantarkan energi lewat kekuatan gerak yang terjaga, presisi yang menggetarkan. Berakar dari bela diri Tionghoa, namun di tangan para penari Semarang, tari ini menjelma menjadi puisi tubuh: menyatu antara kekuatan dan kelembutan, antara kedisiplinan dan kebijaksanaan. Ia adalah tubuh yang berbicara lintas etnis, mengguratkan pesan multikulturalisme di panggung yang basah oleh gerimis.
Lalu Tari Mangzhong—terinspirasi dari siklus agraria dalam penanggalan Tiongkok—mengalun seperti mantra. Mangzhong, “waktu menanam benih”, bukan hanya bicara tentang tanah, tapi tentang gagasan, nilai, dan kebudayaan. Para penari seperti roh musim, membangunkan kesadaran bahwa ada saat yang tak bisa ditunda. Tarian ini menjelma menjadi seruan: tanamlah ide, rawatlah nilai, sebelum musimnya berlalu.
Kedua tari ini, dalam harmoni dan kontrasnya, membuka panggung bukan hanya secara teknis, tetapi secara batin: bubak—sebuah pembukaan, bukan sekadar acara, tetapi cakrawala baru.
Kala Pendekar Bangkit dari Lembaran Mitos
Lalu tirai diangkat. GSAC mempersembahkan lakon “Pendekar Rompi Macan”—sebuah pentas yang tak hanya menghadirkan lakon, tetapi membuka gerbang menuju mitos, sejarah, dan pergulatan batin manusia.
Dengan latar Klenteng See Ong Kiong yang dibalut cahaya, pentas ini tak hanya menjadi suguhan visual, melainkan semacam meditasi kolektif: tempat di mana estetika, spiritualitas, dan sejarah bersatu.
Tri Subekso, sang produser dan inisiator, merancang panggung ini sebagai pertemuan antara tradisi dan tafsir masa kini. Di tangan sutradara Bagus Taufiqurrohman, “Pendekar Rompi Macan” tidak hanya dipentaskan—ia dihidupkan, diberi jiwa, dan diselami maknanya. Tokohnya tak hanya digambarkan sebagai pahlawan, tetapi sebagai manusia yang rapuh, ragu, dan penuh tanya—seperti kita.
Musik garapan Nicodemus Raka Manggala menyusup perlahan, kadang gemuruh seperti perang batin, kadang sunyi seperti doa. Tak hanya menjadi latar, tapi menjadi jembatan rasa. Gerak para penari di bawah koreografi Aprysca Rima Kutria tidak menari untuk ditonton, tetapi untuk dirasakan—setiap ayunan lengan adalah ratapan, setiap hentakan adalah perlawanan.
Artistik panggung yang digarap Septa Adya Anoraga bukan sekadar ruang, melainkan semesta. Ia bisa menjelma menjadi hutan, medan tempur, hingga ruang batin. Cahaya dan bayangan digunakan seperti lukisan jiwa: menggambarkan ketakutan, harapan, dan pertarungan psikologis.
Sementara itu, Khotibul Umam—penulis naskah—menenun kata demi kata seperti penyair yang tengah menenun jaring takdir. Dialognya bukan sekadar percakapan, tetapi mantra yang memanggil emosi, mengguncang batin. Kadang getir, kadang mengharu biru, selalu mengundang renungan.
Dan di balik kerumitan produksi yang luar biasa, Joshua Alvin Pradipta hadir sebagai pimpinan produksi—dalang yang tak tampak, tapi menentukan harmoni. Ia mengikat seluruh elemen menjadi satu: hidup, mengalir, dan utuh.
Zaman yang Bergolak, Nurani yang Berpendar
Lakon ini mengangkat latar yang jarang disentuh: abad ke-18, kala “Geger Pecinan” membakar Semarang. Di tengah kobaran dendam dan pembantaian, lahirlah tokoh yang berjalan di antara bara dan luka: Pendekar Rompi Macan. Ia bukan bangsawan, bukan penjilat kekuasaan, tetapi utusan nurani rakyat.
Rompinya, bersulam loreng harimau warisan leluhur, bukan lambang kekuatan, tetapi simbol keberanian untuk berdiri di antara yang bertikai. Pendekar ini tak berpihak pada kekuasaan manapun—hanya kepada mereka yang terluka dan terpinggirkan. Ia menjadi suara bagi yang bungkam, dan jembatan bagi yang terpecah.
Sunan Kuning pun hadir dalam cerita ini: bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi nyala spiritualitas yang membakar ingatan kolektif. Dalam gerak dan dialog, pertanyaan-pertanyaan besar dihadirkan: siapa yang sesungguhnya pahlawan? dan siapa yang ditinggalkan sejarah?
“Pendekar Rompi Macan” bukan hanya kisah. Ia adalah cermin zaman. Ia memaksa kita bercermin pada luka-luka hari ini—bahwa dendam tak menyelesaikan, dan bahwa keberanian sejati adalah keberanian untuk berdamai.
Ketika lampu panggung padam dan penonton perlahan meninggalkan halaman klenteng, sesuatu tetap menyala di dada mereka. Bukan hanya tentang lakon yang hebat, atau artistik yang memukau, tapi tentang suara nurani yang diam-diam telah dibangunkan kembali.
Karena sejatinya, seni yang besar bukan yang membuat kita bertepuk tangan, tapi yang membuat kita pulang dengan pertanyaan. Sebuah tontonan dan tuntunan bergizi . Tabik, GSAC !
*) Jurnalis dan Penyuka Taeter Tinggal di Tembalang, Semarang.