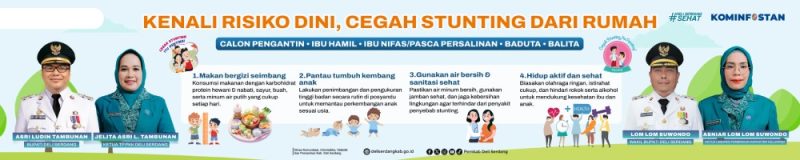Oleh Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Sumatera Post tinggal di Semarang.
Di balik gemerlap sorot lampu dan gaung gamelan yang menggetarkan Gedung Ki Narto Sabdo, ada sosok yang bekerja dengan tekun namun jarang tampil ke depan panggung. Dialah Sunarno, salah satu sutradara legendaris Wayang Orang Ngesti Pandowo, yang dengan tangan dinginnya menenun lakon, meramu gerak, dan menyulam pesan budaya agar tetap hidup di hati penonton lintas generasi.
Sunarno bukan sekadar pengatur panggung. Ia adalah pamomong, seorang pengasuh bagi kesenian dan bagi para pelaku di dalamnya. Dalam lakon Kresna Duta—yang ia garap bersama Wiradyo—ia menampilkan tokoh Prabu Mastwapati dengan tafsir yang bukan hanya menghadirkan kuasa, melainkan juga kebijaksanaan, tanggung jawab, dan ketulusan hati.
Maka baginya regenerasi bukan hanya soal siapa yang bisa menari atau berdandan menjadi tokoh. Yang lebih penting adalah mewariskan nilai: kesatria, kejujuran, gotong royong. Kalau nilai itu tertanam, wayang akan tetap hidup dalam diri generasi muda. “Wayang orang bukan sekadar tontonan, tetapi juga tuntunan; tempat di mana publik bisa bercermin tentang kepemimpinan, kesatria, dan kemanusiaan,” tandas Sunarno.
Sebagai sutradara, Sunarno memahami betul bahwa mempertahankan Ngesti Pandowo bukan perkara mudah. Ia pernah merasakan getir ketika kelompok ini kehilangan panggung permanen, berpindah dari gedung ke gedung, hingga harus tampil di ruang-ruang yang seadanya. Biaya produksi kerap tak sebanding dengan hasil, sementara promosi masih terbatas pada cara-cara tradisional. Namun dari kesulitan itu, Sunarno belajar tentang keteguhan. Ia sadar, seni tradisi hanya bisa hidup jika mau beradaptasi dengan zaman.
Maka ia membuka jalan: mendorong promosi digital, merangkul generasi muda, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Bagi Sunarno, regenerasi adalah kunci. Anak-anak, mahasiswa, hingga seniman muda harus diberi ruang untuk mengenal, mencintai, lalu mengembangkan wayang orang sesuai dengan zamannya.
Ada satu kisah yang kerap ia ceritakan dengan mata berbinar. Suatu malam, pertunjukan berlangsung di TBRS dalam kondisi listrik yang tiba-tiba padam. Lampu sorot mati, suasana panggung gelap, penonton mulai resah. Namun para pemain, dengan aba-aba gamelan yang terus berbunyi, melanjutkan lakon dalam gelap gulita. Dan ketika cahaya kembali menyala, penonton berdiri memberikan tepuk tangan panjang. “Saat itu saya merasa,” kenang Sunarno, “bahwa wayang orang bukan hanya soal panggung megah. Ia adalah nyawa yang hidup dalam dedikasi pemain dan cinta penonton.”
Kini, ketika Ngesti Pandowo telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nama Sunarno tercatat sebagai bagian dari denyut yang menjaganya tetap hidup. Ia bukan sekadar menjaga tradisi, tapi juga mendialogkannya dengan modernitas.
“Wayang orang tidak boleh hanya jadi monumen,” begitu ia pernah berujar. “Ia harus jadi taman, tempat gagasan tumbuh, dan tempat generasi baru menemukan jati dirinya.”
Untuk itu, lanjutnya, Wayang orang tidak boleh hanya hidup di gedung. Di jalan, ia menemukan kembali napasnya—menyapa rakyat tanpa jarak. Wayang on The Street bagi saya adalah cara mengembalikan seni ini pada asalnya: seni rakyat.
Sementara itu, kalau dulu promosi dilakukan dengan memukul bende keliling kampung, sekarang panggung kedua kita adalah media sosial. “Anak-anak muda melihat wayang di layar kecil dulu, baru kemudian datang ke panggung besar. Itu jembatan yang harus kita rawat, ” ujarnya.
Sunarno adalah penjaga api itu. Api yang terus menyala, kadang kecil kadang besar, namun tak pernah padam—api yang menerangi panggung, menghidupi Ngesti Pandowo, dan menjaga wayang orang tetap menjadi denyut kebudayaan Semarang, Jawa, dan Indonesia.
“Saya percaya, selama ada semangat gugur gunung, wayang orang tidak akan punah. Karena wayang bukan hanya milik seniman, tapi milik kita semua sebagai bangsa.”ujarnya optimistis. (*)